NO, YOU’RE NOT
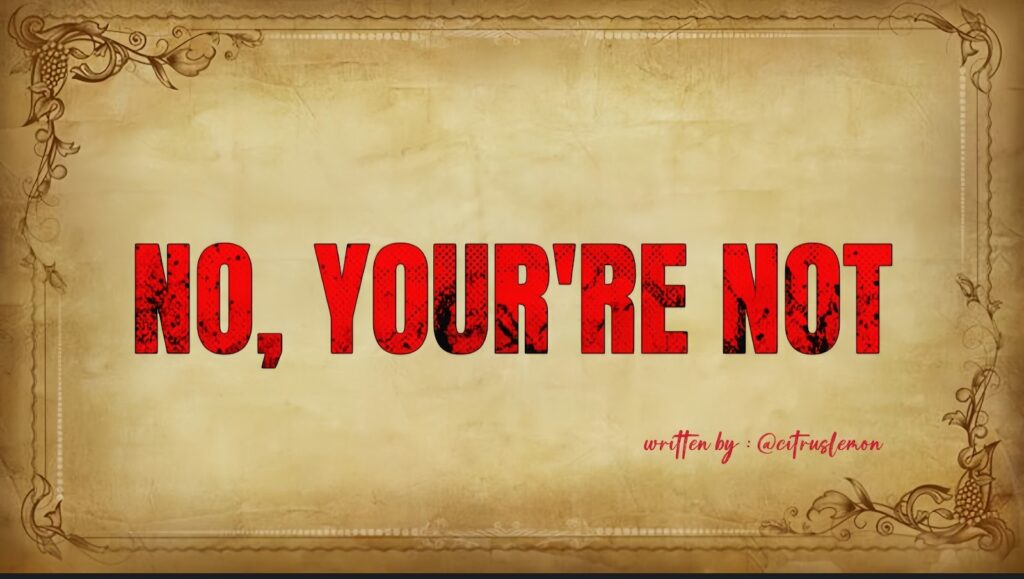
Tags: NSFW, Psychological themes, dysfunctional family dynamic, abusive relationship, coercion, trauma, manipulation, emotional distress, power imbalance, dark theme, violence, confinement, crime elements.
Cerita ini bersifat fiksi dan ditulis untuk keperluan naratif, pembaca disarankan membaca tags dengan kewaspadaan dan lebih bijak dalam menyikapi antara fiksi dan fakta. Adapun semua tindakan buruk dan perilaku negatif yang ada di dalamnya tidak bisa membenarkan tindakan dan perilaku serupa di kehidupan nyata. Semoga, pembaca bisa menikmatinya sebagai karya, bukan sebagai dasar atau contoh dalam perilaku di dunia nyata.
Jeon Jungkook fanfiction; Jungkook As Juan and Jane as Female Reader
🎀ྀིྀིDitulis oleh Citruslemon hanya untuk hiburan semata🎀ྀིྀི
────୨ৎ────
Aku sudah menduga apa yang akan menyambutku dibalik pintu. Setiap hari, sejak dulu, setiap aku pulang sekolah, hingga kuliah—saat ini. Dan dugaanku benar. Rumah mewah dengan interior super megah berlapis aroma pengharum ruangan menyesaki udara, rumahku, rumah orang tuaku. Tapi bukan itu.
Selain menyisakan kekosongan panjang dan kesepian akut karena orang tuaku nyaris tak pernah ada di rumah, hunian yang lebih mirip kastel ini juga diisi oleh Juan, kembaranku. Lalu pelayan-pelayan yang terlihat seperti tak bermulut.
Setidaknya, itu yang dikatakan orang tuaku seumur hidup–atau kurang dari itu; Juan dan Jane adalah kembar. Kalian kembar tidak identik yang manis. Dia kakakmu, kembaranmu. Jarak kalian hanya setengah jam.
Aku mempercayainya hampir sepanjang hidupku. Lagi pula tak ada alasan untuk tidak mempercayainya.
Hingga malam itu datang. Tapi aku sedang tidak ingin membahasnya.
Juan menyugar rambutnya yang berminyak ke belakang saat pintu depan terbuka—maksudku, rumah ini difasilitasi pelayan–untuk sekedar menarik grendel yang tak akan menghabiskan banyak energi. Bahkan, aku masih memiliki pengasuh hingga usia ini—yang bersedia menarik gagang pintu dengan mulut jika aku memintanya.
Tapi pria itu selalu bersedia repot–tergopoh cepat-cepat membuka pintu saat jadwal pulangku yang nyaris tak pernah berubah datang. Tubuhnya basah oleh keringat khas lepas sibuk berkutat dengan alat gym bodoh yang semakin membuat pria itu mirip monster mengerikan. Benar-benar dungu, di mataku, Juan sangat dungu dan tolol. Melihat wajahnya saja membuatku jijik. Senyumnya naik menyambutku yang nyaris tak pernah bermimik ramah. Di mataku, pria itu mirip setan dan aku ingin sekali meludahi wajahnya.
Tentu, aku tentu saja memiliki alasan mengapa aku begitu membenci kakakku.
Yang pertama karena dia dungu. Dia hampir menghabiskan seluruh hari-harinya dalam rumah. Mengambil kuliah daring dan terus berperilaku sebagai orang tuaku saat orang tua kami tidak ada.
Yang kedua karena dia terus membuntutiku seperti stalker gila. Juan selalu menemukanku kemanapun aku pergi. Maksudku, aku adalah gadis pada usia dimana bermain dengan teman-teman adalah lumrah. Aku bermain layaknya anak seusiaku bermain. Aku tidak memakai narkoba, tidak seks bebas, tidak mengikuti sekte sesat, bahkan tak memiliki kekasih. Namun satu jam setelah aku sampai rumah temanku, atau kafe, dan apapun tempatnya, dia akan datang lalu menarikku pulang seakan aku baru saja menebar kultus sesat.
Matanya seperti macan yang kutemui di kebun binatang 5 tahun yang lalu. Nyalang sekaligus sendu.
Aku hanya melihatnya beberapa detik sebelum akhirnya pintu tersebut kubanting menutup. Di atas tegel dingin, telingaku di gedor oleh pacu jantung. Mulutku ingin sekali menyumpahinya dengan rentetan caci maki. Aku benar-benar membencinya sepanjang hidupku.
Ingatanku berputar kembali, mencoba merunut peristiwa demi peristiwa yang terjadi hari ini. Mungkin roti yang kubeli di toko kue tadi pagi kadaluarsa. Atau bisa jadi sup di restoran siang ini mengandung jamur yang melepaskan gas kebencian dan membuatku semakin membencinya dari hari ke hari. Rasanya sampai ingin muntah. Dan itu juga menyakiti diriku sendiri.
Tapi, tidak. Roti tadi pagi rasanya baik-baik saja dan sup jamur di restoran langgananku sama seperti biasanya, semuanya normal. Senormal pengasuhku yang muncul membawakan tas dan memberitahu jika ayah dan ibuku akan kembali terbang ke Timur Tengah setelah sebelumnya berada di Asia Timur. Mereka bahkan tidak perlu repot-repot pulang hanya sekedar menengok anak-anaknya yang kesepian luar biasa. Atau mungkin hanya aku? Sialan Juan, aku tidak tahu isi kepalanya. Kupikir otaknya tersusun dari kotoran yang membentuk struktur otaknya sekarang. Dia menikmati perannya menjadi pengganti orang tuaku dengan segala sabda tololnya.
Suatu waktu, dalam perkumpulan sederhana makan malam, ayahku mengatakan jika Juan adalah waliku selama mereka tidak ada. Aku harus akur dan patuh padanya. Dia adalah kakak yang baik. Dia akan menjagaku. Pula dikatakan seformal mungkin seakan kami bukan sedang makan malam, melainkan pertemuan kongres.
Itu dia, mungkin kata-kata itu yang membentuk kebencianku semakin membumbung tinggi.
Beringsut malas, aku melempar kaos kaki sembarangan yang langsung dipungut pengasuhku. Aku merasakan gemuruh jengkel di dadaku yang berimbas pada getar halus kakiku saat bertolak menuju kamar.
Tidak sudi menoleh ke belakang.
────୨ৎ────
Apa yang paling didamba setelah seharian berkutat dengan tugas dan serangkaian diskusi yang menguras isi kepala? Tidur, tidur yang nyenyak dan nyaman tanpa gangguan, tanpa suara repetitif yang memaksa kesadaranku kembali. Aku seharusnya masih mendapatkannya, jika bukan ulah manusia sialan bermata mirip macan yang ditinggal kabur ibunya.
Dirasa mengacaukan hidupku dengan terus ikut campur ini dan itu tidak cukup efektif, Juan mulai mengguncang tubuhku, memainkan knop pintu, memukul-mukul tralis jendela. Namun dari semua hal, yang paling menyebalkan adalah, manusia sialan itu memainkan lampu kamar. Mati, hidup, mati, hidup. Aku seolah tidur di klub malam. Lalu suara cekikikan menyusul dari bibir dengan ujung bertindik yang semakin terlihat mengesalkan di mataku.
Apa menurutnya ini lucu?
Atau ada hari dimana dia masuk dalam kamarku, memati hidupkan lampu, atau sekedar menjatuhkan tas atau gantungan baju. Lalu keluar sambil terbahak-bahak.
Sudah kubilang, isi kepalanya adalah kotoran yang tersusun menjadi struktur otak.
“Jane.. makan hey.. Lu belum makan dari pulang kampus. Ada kepiting lada hitam. Gua yang masak. Sumpah, lu pasti ketagihan” Juan mulai menggelitik kakiku.
Mataku terbuka. Kuhirup oksigen sebanyak-banyaknya hingga dadaku terasa sesak–untuk bekal napas supaya caci maki tak terpotong karena aku mudah menangis dan kehabisan napas.
“Bajingan!! Bangsat!! Lu sinting ya? Gila! Anjing banget” aku tau Juan kaget mendengar suara lantangku yang menggema hingga koridor. Lampu tak berkedip lagi dan tiba-tiba semua terasa hening beberapa detik.
“Lu nggak tau betapa lelahnya gua pulang dari kampus karena tugas! Beda sama lu yang antisosial dan memilih kuliah di rumah mirip nolep menjijikan. Gak ada sosialisasi, hidup menyedihkan dan nggak bergaul. Makannya nggak normal otak lu” benar, padahal aku sudah menghirup napas panjang tadi. Namun aku masih terengah dan tenggorokanku tercekat. Kuperhatikan ekspresi Juan yang mengerutkan dahi. Mata sayunya seakan berubah mirip mata ikan di pasar. Pucat.
Namun hanya sebentar. Aku sudah hafal, begitu hafal hingga muak dan berharap dia akan sakit hati atas ucapanku. Atau sekedar lelah dan berhenti melakukan hal tidak berguna untuk akrab dan berlagak menjadi wali sialan.
Dalam kurun 3 menit, ekspresi kaget dan pucat itu berganti. Seperti cadangan baterai nya begitu banyak dan anti sakit hati. Mungkin itu juga yang membuat mulutku semakin mengerikan padanya. Terabas, tanpa aling-aling.
“Gua abisin kalau lu nggak cepet bangun. Koki lagi sakit dan hari ini pelayan masak mirip muntahan anjing, lu akan menyesal kalau nggak cepat turun dan makan” aku melihat senyum itu sudah kembali dan bagaimana caranya mengulum tindik di sudut bibir benar-benar membuatku mual.
“Jane Juan, Jane Juan, Jane, Juan, Jane, Juan” aku mendengarnya hampir mirip doa-doa yang dipanjatkan penganut ajaran sesat, mulutnya komat-kamit sementara tangannya sibuk menarik kakiku hingga tubuhku menggantung separuh–antara lantai dan kasur. Jangan tanya bagaimana aku ingin membalasnya.
Dan Juan tentu saja berlari saat aku mulai mengambil apa saja untuk kulempar.
Sok akrab.
Juan adalah kembaranku, namun kami tidak pernah satu sekolah, aku bahkan tidak tahu dia sekolah atau tidak. Jika aku pulang sekolah, dia sudah ada di rumah. Begitu juga perguruan tinggi. Dia mengatakan kuliah daring tapi aku benar-benar tidak paham dengan sistemnya.

Cangkang merah-oranye gelap tertutup lapisan saus yang kental, pekat, dan berkilau. Ini adalah favoritku.
Baik, aku akan mengakui yang ini. Selain kurang kerjaan dan di mataku dia adalah nolep menyedihkan, sebenarnya Juan begitu pandai memasak, pintar membenarkan apapun yang rusak seperti barang elektronik dan sejenisnya. Dia juga pandai menjahit, melakukan pekerjaan rumah yang tidak perlu, serta mencari tambahan uang jajan dari dalam kamarnya—meski aku tidak tahu apa yang ia kerjakan. Namun pernah sekali, ia pamer padaku dan mengatakan lepas menjual produk digital yang tidak kumengerti dan sama sekali tak kuminati.
Dia memperhatikan ketika aku makan. Saat melihat suapan lahapku, dia akan tersenyum kelewat tinggi hingga aneh. Lalu mulai menawarkan ini dan itu—makanan tambahan yang kuyakin bukan buatannya—meski ia pandai memasak.
“Mami sama Papi ke Timur Tengah, gua pikir lu belum tau” suara itu memecah hening dan menjadi teman denting sendok dan piring. Aku tidak menjawab karena sudah tau. Saat kulirik dengan ekor mataku, Juan sibuk dengan laptopnya. Sebenarnya, aku tidak tahu apa guna eksistensinya di meja makan. Dia tidak menyentuh makanannya, tidak juga cemilan. Hanya sesekali meneguk robusta dengan aroma memikat.
“Jangan terlalu dekat sama cowok yang namanya Julian. Dia playboy dan hampir tiap malam ganti-ganti teman tidur. Dia juga mokondo”
Baru ketika topik yang bertolak begitu jauh dilontarkan, aku menahan kunyahanku. Berhenti mendadak dan jujur mulai malas melanjutkan makan. Kepalaku cepat mencari spot nyaman untuk menusuknya dengan mataku.
Dia stalker gila. Dia tau hampir semua informasi tentang teman-temanku, tentang pria yang sering aku dan temanku bicarakan saat mengobrol–Julian adalah salah satunya. Meski jengkel, aku tidak akan repot bertanya; dari mana dia tau? Atau marah. Aku lapar. Dan hal seperti itu sudah lumrah. Juan tau semua hal dan aku tidak pusing. Membencinya saja sudah merepotkan. Setidaknya, aku akan menghabiskan kepiting.
“Mau keluar malam ini? Ada festival tahunan dekat alun-alun. Ada banyak makanan enak dan minuman manis. Gua pikir lu akan suka” debam halus laptop yang ditutup, kopi yang tinggal setengah itu diteguk cepat padahal aku bersumpah itu panas.
Aku menggeleng, tentu saja.
“Berhenti sok akrab dan—” aku hampir tersedak, Juan memberiku minum cepat-cepat.
“Gua abang lu, jangan terlalu galak” katanya perhatian. Namun jenis perhatian yang jelas membuatku merinding. Aku bahkan tidak bisa melihat lurus pada detail wajahnya—tidak pernah karena malas. Teman-temanku bilang, Juan adalah pria tampan dan keren. Otot kekarnya bisa untuk ganjalan tidur malam yang nyaman—juga karakternya yang dingin mirip dalam tokoh-tokoh khayalan bodoh. Sudah kubilang mereka harus berhenti membaca novel picisan.
Demi pendingin dengan suhu kelewat rendah, aku tidak ingin mencaci makinya lagi meski ingin. Maksudku, biarkan aku makan dengan tenang. Juan hampir tak pernah pergi dengan teman-temannya, dia sibuk, katanya. Entah jenis kesibukan seperti apa. Namun saat ia bermonolog di kamarku; sebenarnya mengajakku berbincang, namun aku tak merespons nya sedikit pun. Dia terus mengatakan jika dia memiliki teman, mereka bertemu sesekali meski aku bersumpah tidak pernah mendapati omong kosong itu.
“Gua tunggu di depan, ya?”
“Gua nggak mau, nggak sudi. Lu kenapa sih?” sorotku galak. Jika aku bercermin, aku akan takut melihat wajahku sendiri. Aku pernah mencobanya.
“Lu akan bosan, gua udah pesen meja dekat stand bagus. Ada teman gua jualan disana”
Aku tidak melihatnya, tidak juga menjawab.
“Jane”
“Gua mau mati aja ketimbang ikut lu main. Nggak berguna, lu cuma berhalusinasi bilang punya teman. Nggak ada satupun makhluk di bumi ini yang mau berteman sama lu, freak”
Aku membanting piring. Kulihat dua pelayan yang berdiri di pojokkan kaget karena suara keras tiba-tiba. Aku juga tau mereka kerap membicarakan tingkahku yang keras dan kasar. Sesekali ku dengar mereka berbisik menyayangkan Juan yang memiliki kembaran sepertiku. Mereka hanya tidak tahu kenyataannya. Pelayan berwajah ganda, aku bersumpah akan memecat mereka jika kelakuan itu tak berubah. Sementara orang tuaku tidak tahu. Tidak tahu, mungkin tidak peduli juga jika aku membenci Juan karena dia bertingkah sok. Kami seumuran, itu melukai harga diriku.
Aku sampai dalam kamar ketika kuputuskan untuk tidak menghabiskan makan sore. Dalam kamar, kulihat rentetan tugas yang menunggu disentuh. Catatan-catatan kecil yang sama sekali tak kulihat lagi setelah terakhir aku menulisnya. Aku menghela napas. Bayangan festival, jajanan, minuman manis serta keramaian yang menyenangkan tiba-tiba merangsek—tentu saja mengalahkan catatan-catatan dari kertas binder yang kutempel miring pada papan list.
Sial.
Aku kesal sendiri.
Kupalingkan pandangan dari list tugas pada ponsel yang menyala. Denting pelan berhasil membuatku mengangkatnya.
Pesan dari temanku.
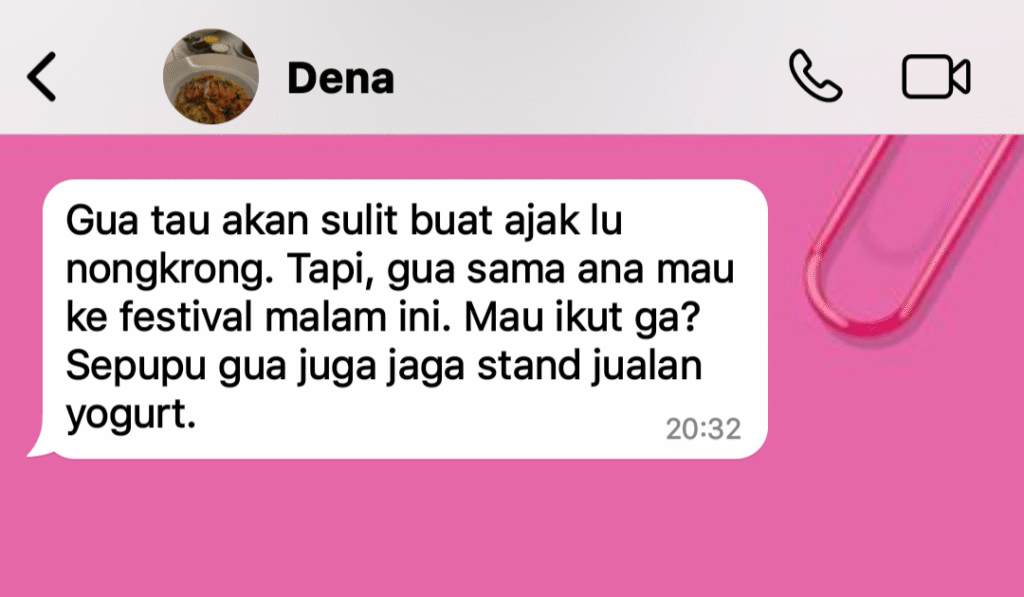
Aku masih menatap rentetan abjad yang menyusun kata-kata Dena.
Aku sebenarnya anak manis yang terkenal paling pendiam dan malu-malu di antara semua teman-temanku. Hanya saat bersama Juan, aku menjadi bukan aku. Padahal, aku mudah menangis dan tidak bisa membentak orang. Jika kupaksa lakukan, aku yang akan menangis. Dan aku sering menangis di depan Juan karena memohon agar sikapnya tidak menyebalkan. Namun tampaknya dia memang tidak ingin akur denganku.
Aku tak segera membalas pesan dan Dena meneleponku.
────୨ৎ────
Dan disinilah aku berdiri.
Satu tangan memegang smoothie stroberi, tangan yang lain mencengkram erat bungkusan berisi jajanan tak sehat–yang jika ini adalah belasan tahun lalu dan ibuku tau, maka, dia akan mengomeliku dengan gayanya yang khas; canggung dan tidak natural. Jenis omelan yang tidak akan di dengarkan anak bangsat manapun. Oh betapa aku rindu. Meski itu satu-satunya kenangan tidak penting dan hanya itu yang paling membekas karena memang tidak ada kenangan lainnya lagi.
Pun hampir terjadi terakhir ketika aku duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Makin kemari, ibuku benar-benar sibuk dan kami semua mulai bersikap formal. Mereka yakin jika aku mampu menyelesaikan masalahku sendiri, apabila menemukan kesulitan, aku diminta mendatangi Juan.
Aku berdiri dan Juan hampir merangkul pundakku meski berkali-kali ku tepis kasar. Dua temanku tak kunjung menampakkan diri.
Sebenarnya, aku adalah gadis yang sama sekali tidak pernah berpacaran, tidak pernah memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis–hampir tak memiliki kontak laki-laki selain Papi, Juan, dan sopir. Yang kulakukan hanya sekolah, belajar, bermain di rumah saat teman-temanku datang–karena aku jarang sekali keluar.
Tapi tak menutup diri jika teman-temanku membahas kekasih mereka. Atau idola Korea dan beberapa pria tampan yang ada di kampus. Hanya sebatas itu.
Pun jika ada yang meminta nomorku, mereka hanya akan mengirimkan pesan satu sampai dua hari. Setelah itu nomornya menghilang seakan tidak pernah ada. Aku tidak perhatian dan memang tidak peduli.
Maka, yang dilakukan Juan sekarang kupikir beralasan.
Aku tidak menghitung jumlah mereka. Namun sepanjang jalan kami menyusuri stand-stand sambil menunggu acara dimulai, begitu banyak pria-pria aneh yang melontarkan catcalling. Beberapa ada yang terang-terangan mendekat dan meminta kontak. Awalnya Juan memang hanya berjalan di belakangku, namun saat orang-orang makin aneh, dia mendekat dan kami beriringan. Dia juga mencoba merangkul pundakku meski rekasiku lebih kasar padanya ketimbang pada pelaku pelecehan verbal.
Tentu, itu membantu. Tubuh mirip monster itu akan membuat kicep para berandal.
Aku tidak peduli.
Saat kusisir dongak ke dalam matanya, aku melihat cahaya jingga yang terpantul di antara pupil legamnya. Ia sedang melihat stand tempat dimana bunga palsu yang berkilauan hingga menyorot jauh ke matanya yang sendu. Saat kuikuti kemana fokus itu berlabuh, Juan menawariku untuk mampir. Aku kontan menggeleng. Meski aku penasaran dan suka, aku akan tetap menolak. Ini untuk harga diriku, tentu saja.
Stand bunga tertinggal di belakang. Kami menuju tempat duduk yang katanya sudah di pesan Juan entah pada siapa. Namun belum sampai, tepukan pada bahuku membuatku langsung berbalik.
Dena dengan setelan imut. Menggunakan dress lucu serta sepatu berpita senada, kaus kakinya hampir menyentuh paha. Berbanding dengan Ana yang berpakaian serba hitam, keduanya tersenyum tinggi saat menemukanku—lebih tepatnya senyum pada Juan malu-malu.
“Nyangka gak lu?” ada serak di antara suara, Dena bertanya pada Ana sementara matanya mencuri-curi pada Juan “biasanya susah banget ajak Jane keluar. Coba? Ini jam 8 malam dan Jane keluar. Gimana perasaan anda?” tanya nya berlebihan. Kuharap, telinga Juan menangkapnya sebagai sarkas.
Aku nyengir kuda dan tidak menjawab.
Semua teman-temanku tahu betapa aku sulit keluar. Semua orang di rumah, pelayan, sopir bahkan orang tuaku yang sekarang entah berada dimana aku lupa, mereka akan lebih mendengarkan Juan ketimbang aku. Hanya bayangkan saja jadi aku.
Dan sialan itu hanya memasukkan dua tangan dalam saku celana, berjalan lambat dan lagi-lagi hanya memantau dari belakang. Dia memberitahu Dena tempat duduk kami dan mulai bertingkah seperti pengawal pribadi yang melanggar aturan. Kuharap ia hilang akal dan lupa jalan pulang.
“Julian tanyain alamat rumah lu karena tiba-tiba nomornya lu blokir. Dia bilang apa ada yang salah, dan dia ragu mau dm lu lewat insta” dan tentang stand yang di pesan khusus, Juan tidak berbohong. Kami duduk bertiga di sofa empuk meski hampir semua orang berdiri atau mengenakan kursi plastik. Pernyataan Dena tentang aku memblokir Julian membuatku berhenti menyedot minuman kelewat manis dengan kalori setara dengan 10 porsi makan sore tadi.
“Gua nggak memblokir Julian” kataku tegas. Aku hampir tidak pernah memblokir siapapun dalam kontakku kecuali mereka sendiri yang menghilang. Kupikir ada yang tidak beres dengan caraku berinteraksi, atau sesuatu yang tidak bisa diterima–maka, aku tidak terlalu perhatian pada beberapa kontak yang menghilang tiba-tiba karena kupikir mereka tidak lagi tertarik bertukar pesan denganku. Namun saat Dena mengatakan aku memblokir Julian, kurasa terjadi kesalahan disini.
“Lu memblokir dia” kali ini suara Ana, mulutnya sibuk mengunyah permen karet. Katanya untuk melatih rahang atau apalah. Lantas, aku cepat-cepat mengeluarkan ponsel. Melihat daftar blokir dan untuk pertama kalinya aku memeriksa.
Sekitar 10 orang berada dalam list; aku memblokirnya.
“Tukan!” tukas Dena sambil memukul pahanya sendiri. Aku masih mengernyit tidak percaya. Aku hampir tidak pernah mabuk, tidak pernah teler, tidak pula memiliki gangguan tidur sambil berjalan atau sejenis. Aku bersumpah tidak pernah memblokir siapapun dalam hidupku. Itu membuatku bingung.
Tunggu, sebenarnya, aku adalah anak manis. Aku akan terus memvalidasi ini. Kecuali, kecuali Juan. Dan entitas itu satu-satunya kandidat yang bisa melakukan ini—melakukan hal seperti mengetahui dimanapun posisiku, apa yang kulakukan dan siapa saja—mungkin yang menghubungiku. Atau, dia juga bisa memblokir nomor pada ponselku. Ah sial, aku ingin membunuhnya sekarang juga.
Saat kulirik ke belakang, Juan sibuk menerima panggilan. Atau itu akal-akalannya saja ketika berhasil menguping pembicaraan kami. Aku yakin demi hidupku, pelakunya adalah Juan.
Matanya praktis menatap lapangan secara presisi. Tarian tradisional akan dibawakan anak-anak usia 4 tahun dalam rangka ulang tahun kota. Juan bersedekap fokus ke sana meski ku yakin dia tahu aku menatapnya seperti akan menguliti.
────୨ৎ────
Satu minggu sejak kucecar dengan ancaman yang jelas gagal menakutinya. Atau sekedar membuatnya harus mengakui apapun karena itu adalah tindakan kriminal.
Menyadap ponsel. Itu tindak kriminal.
Juan mengatakan tidak, tapi tidak mau melihat ke mataku. Dia terus mengalihkan tatapan sambil berkelit dan menyanggah seluruh tuduhanku. Dia bahkan meminta bukti atas apa yang diberatkan padanya.
Dan, lagi. Aku menggeledah kamarnya, membuka komputer yang berjajar banyak dengan trafik rumit yang sama sekali tidak kumengerti. Aku juga membuka ponselnya berusaha mencari apapun sebagai bukti bahawa dia telah meretas ponselku. Tapi nihil, aku tidak menemukan apapun. Itu semakin membuatku jengkel.
Itu seminggu yang lalu. Aku menyerah dan mulai mengabaikannya, aku juga sempat pergi menemui seseorang yang kata teman-temanku ahli dalam bidang itu—mengetahui apakah ponselku disadap atau sejenis. Dan tukang itu mengatakan ponselku bersih. Tidak ada perangkat mencurigakan yang memiliki kontrol atau aplikasi yang biasanya dipakai pelaku peretasan, bersih. Saking bersihnya sampai aneh.
Aneh, karena aku memblokir nomor orang-orang tanpa ingatan tentang itu. Apa aku sungguh melakukannya saat tidur?
────୨ৎ────
Hujan deras baru saja berhenti beberapa waktu lalu. Di antara suhu yang membekukan favoritku, pengasuhku mengetuk pintu dan mengatakan jika aku memiliki tamu.
Tidak, bukan Dena, bukan juga Ana. Aku juga penasaran karena tidak ada notifikasi apapun dari siapapun yang akan bertamu ke rumahku.
Dan itu tidak terlalu bagus—maksudku, Julian.
Aku turun bersama kaos kebesaran dan celana yang tenggelam oleh atasan—mengenakan sandal rumahan berbentuk kelinci yang mengubur seluruh permukaan kaki, kuseret langkahku menuju ruang depan.
Julian dan Juan.
Kembaran palsuku duduk menyilangkan kaki di seberang sofa tempat di mana tamuku duduk. Mereka berhadapan. Tidak, aku berpikir jika situasi ini lebih mirip seperti penyidik menginterogasi pembunuh berantai. Tatapan Juan tak enyah, tak kedip, mirip macan lapar yang siap menerkam mangsa. Sementara Julian mengapit dua tangan di antara paha sambil tertunduk–terintimidasi. Astaga, apa dia tidak tahu jika Juan seumuran dengannya? Pasti harga dirinya akan terluka juga, seperti aku.
Dari tangga, aku sama sekali tak mendengar percakapan. Mereka hanya diam saja seperti itu. Saling memperhatikan, saling mengintimidasi lewat tatapan–meski hanya dilakukan Juan. Pria itu sangat sok, kendati tubuhnya jauh lebih besar dan kekar, seharusnya tidak seperti itu. Begitu banyak alasan pendukung mengapa dia tidak memiliki teman.
Saat melihatku, Julian seperti anak kelinci yang terbebas dari terkaman macan. Pria itu menampakkan deret gigi bergingsul dengan senyum secerah matahari setelah hujan. Aku duduk di sampingnya, berjarak kurang dari 1,5 meter.
“Maaf, Jane, gua nggak ngabarin mau datang. Kontak gua diblokir dan gua–” pria itu membenarkan suaranya yang baik-baik saja dengan berdehem “gua pikir gua harus meluruskan kesalahpahaman ini”
Aku masih tidak tahu kesalahpahaman jenis apa selain setan gila atau memang aku yang teler lalu memblokir hampir semua kontak pria dalam ponselku.
“Gua ada salah kah? Gua tanya ke Dena alasan lu blokir kontak gua dan dia menjawab terlalu rumit dengan bahasa yang sulit dimengerti. Gua cuma mau dengar dari lu langsung” katanya gugup. Bagaimana mungkin Juan bodoh itu mengatakan jika Julian adalah bajingan gila perempuan sementara di depanku saja, dia gugup dan mudah merona? Pada dasarnya Juan edan itu tidak ingin aku memiliki teman, bersosialisasi, dan terhubung dengan manusia. Dia ingin aku menjadi antisosial saja sepertinya lalu membusuk dalam rumah.
Aku tidak menjawab Julian, belum. Yang kulakukan adalah melabuhkan pandangan pada Juan yang juga menatapku, lalu menatap Julian bergantian.
“Bisa kasih space? Gua lagi ada tamu dan butuh privasi” kata-kataku dingin, kupikir aku sudah mengusirnya dengan cara paling anggun sekaligus tegas.
Karena itu berhasil. Juan bangkit dari kursi, memasukkan dua tangan dalam saku celana lalu melangkah entah kemana. Setelah dia pergi, aku baru kembali pada Julian.
“Sebenarnya, gua udah buka blokiran. Alasannya agak rumit dan gua malas menjelaskan” kataku bingung, aku tidak tahu apakah aku harus jujur mengatakan jika kau teler dan memblokir 10 kontak tanpa sadar. Itu terdengar idiot. “Tapi udah gua buka blokirannya, cuma ya.. Gua belum kirim pesan karena nggak ada konteks untuk dibahas” sambungku kaku.
Julian mengangguk-angguk, lalu mengatakan alasan yang diberikan Dena nyaris serupa denganku. Beberapa detik kemudian, kami sepakat tak membahas kontak yang terblokir. Kami mulai mengobrol seperti air mengalir.
Membicarakan tugas kuliah, cuaca, hal-hal baru yang sedang tren, sampai menanyakan apakah aku memiliki kekasih atau crush. Kami bertukar tanya seperti itu dan kadang tertawa saat terselip sesuatu yang lucu, pun aku–tahu dia juga tahu bahwa aku satu-satunya jomblo di antara dua temanku sejak lahir. Julian hanya berbasa-basi dan aku–mengerti jika dia mungkin saja menyukaiku. Dena mengatakannya sehari 3 kali; Julian menyukaiku.
Adegannya tidak persis seperti novel yang sering kubaca, atau drama romantis saat si pria mengajak gadisnya untuk berkencan. Julian terbata–menatapku salah tingkah. Ia berkali-kali berdehem meski tak ada yang salah dengan suaranya.
“Jane.. lu tau, semua tau.. Gua—” kata-katanya terpotong saat mendengar suara aneh mendekat. Aku ikut celingukan mencari sumber suara.
Juan membawa alat penyedot debu dan membersihkan lantai.
Meski aku pernah mengatakan bahwa dia rajin bersih-bersih, namun dia hanya membersihkan kamarnya. Hampir tidak ada pelayan yang masuk dalam kamarnya karena ia membersihkan sendiri. Namun memegang alat penyedot debu lalu membersihkan lantai hingga ruang tamu, sungguh sangat langka dan ajaib.
Tidak ada yang kotor dengan lantai, pelayan membersihkannya sehari 3 kali. Marmer kelewat mengkilap itu sungguh tidak memiliki debu barang seatom. Ini berlebihan, tapi seandainya siapapun ingin bercermin di lantai rumahku, itu sangat bisa, aku berani jamin.
Julian tidak melanjutkan kalimatnya.
Tidak, kami bahkan tidak melanjutkan mengobrol hingga beberapa saat sampai Juan pergi dengan alat penyedot debu bodohnya. Aku menghela napas dan mewakili kakakku meminta maaf atas ketidaknyamanan itu pada Julian.
“Dia agak… impresif” kata Julian berusaha menggambarkan Juan dalam satu kata yang praktis—yang tidak terdengar seperti pujian kurang natural. Padahal aku lebih senang saat dia jujur dan mengatakan jika Juan adalah idiot sinting haus atensi.
Sesaat, Julian tampak akan kembali mengatur kata-katanya. Agak lama hingga pelayanku datang membawakan minuman yang sama sekali tidak kuminta. Aku bahkan lupa menawarkan minum pada Julian dan tersenyum pada pelayanku yang pengertian. Aku tidak jadi memecatnya jika dia sepeka ini.
Ia menyesap cappucino pelan. Pelayan membawakan itu dengan aroma menggugah, sementara milikku adalah teh hijau hangat yang terlihat bening. Dasar mok terlihat cantik dengan ukiran dedaunan rumit yang kontras dengan hijau muda menggenang di atasnya. Aku memperhatikan itu sembari menunggu Julian melanjutkan kata-katanya.
Tidak lama, Juan terlihat kembali.
Ia hanya berjalan mondar-mandir, ke depan dan masuk, begitu terus hampir tiga kali.
Berakhir merentangkan tangan di teras sambil menguap lebar. Aku tidak mengerti maksudnya.
Sementara aku dan Julian kembali diam.
Tidak ada yang bicara agak lama ketika kami bahkan bisa melihat Juan melakukan pemanasan di depan. Suara berhitungnya kencang seperti pemimpin Abri yang melakukan apel pagi.
Bajingan itu… dia bahkan hampir tidak pernah bersuara keras.
Tiba-tiba suara Julian yang mengagetkanku.
Pria itu mengaduh sambil memegang perutnya. Dia meringis begitu kesakitan hingga membuatku ikut panik.
“Perut gua, akhh!! Perut gua.. No” dia menggeleng-geleng. Satu tangan memegang perut sementara tangan yang lain memegang bokong. Lalu dia hampir menangis, aku makin kebingungan.
Disusul suara buang angin yang aneh—maksudku, itu persis seperti.. Ah.. aku tidak sanggup membayangkannya. Julian bangkit berdiri dan kotorannya keluar berbentuk cairan dan acak-acakan di atas lantai marmerku yang tidak berdebu. Saat kulirik sofa bekasnya duduk, di sana basah dan aroma busuk khas menguar. Julian mencret.
Pria itu buru-buru pamit mencari toilet dan saat pelayan menunjukkan, dia langsung menghilang secepat kedipan mata. Meninggalkan jejak kaki berceceran tahi.
Aku tidak sanggup.
Dan yang kulakukan adalah keluar lalu memuntahkan seisi perutku di teras. Saat aku mendengar Juan tertawa sampai terjengkang ke lantai, aku mulai mengerti.
Minuman tanpa kuminta itu berisi racun. Juan sialan.
Mengapa masih menggunakan metode klise semacam ini? Benar-benar kolot dan payah. Aku membencinya level 10 hari ini. Sebenarnya stabil dari hari ke hari. Nyaris tak pernah berkurang malah kadang bertambah melewati garis.
────୨ৎ────
Julian tidak menghubungiku sama sekali setelah pertemuan terakhir kami. Aku juga tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Dan hidupku berjalan seperti biasa setelahnya, tidak ada apa-apa. Hanya seperti biasa.
Padahal, aku akan meminta maaf jika dia mau menemuiku atau mengirim pesan. Sementara aku sama sekali tak bernyali. Bahkan untuk mengetik maaf pada papan chat. Rasanya berat, maka, kubiarkan saja hingga semua hilang dan seperti tidak pernah terjadi.
Genangan-genangan oranye di antara rerumputan pecah begitu saja di bawah sol sepatuku. Hujan tak berhenti sejak semalam dan sore menjelang petang ini, aku memutuskan untuk ikut kelompokku mengerjakan tugas di kafe terdekat. Aku sudah mengirimkan pesan pada Juan, terserah jika dia mau datang dan melihatku bersama tiga orang lainnya berkutat dengan tumpukkan kertas dan laptop sambil mengisi daya.
Dengan satu tangan, aku meraup beberapa tumpukkan kertas yang berantakan dari kursi mobil. Beberapa kupeluk ke dada, sementara tangan yang lain menjinjing laptop dan tas menyampir dibahu. Sementara kakiku membanting pintu mobil. Alarm mobil menyala singkat kemudian, pertanda pintu sudah kembali terkunci.
Dengan tangan penuh, aku berjalan menuju meja teman-temanku.
“Butuh bantuan?”
Bukan suara salah satu temanku. Tapi familiar lainnya. Secepat kilat tubuhku berputar, siap melempar salah satu yang ada di dekapan atau genggaman. Akan tetapi, gerakkan tiba-tiba tersebut—ditambah jalan yang licin–justru membuatku oleng ke belakang. Aku mungkin harus dilarikan ke rumah sakit jika saja tangan pria itu tidak melingkar di pinggangku.
Ini persis. Aku berada dalam romansa drama yang presisi. Adegan selanjutnya berjalan begitu lambat. Aku yakin seharusnya hanya berlangsung paling lama lima detik. Akan tetapi, dalam waktu sesingkat itu, aku menangkap segalanya. Tangan yang menopang tubuhku. Helaian pekat yang klimis oleh pomade. Bahkan wajahnya yang sedang terkejut tetap manis.
“Lu nggak papa?” itu Julian. Suaranya empuk seperti permen kapas, namun sukses memecah lamunanku–apalagi ingatan tentang kotoran yang bercecer di lantai serta aroma busuk yang membuat trauma.
“Oh.. uh.. Nggak” aku segera menegakkan tubuh “nggak apa-apa, kok. Sorry–umm makasih. Maaf, maksud gua..” bagus, aku ahli sekali dalam hal mempermalukan diri. Namun sejajar dengan kejadian seminggu lalu yang—mungkin saja juga sedang berusaha ia lupakan. Tapi aku segera berjongkok memunguti kertasku yang dekil.
“Seharusnya gua yang minta maaf” dia ikut berjongkok dan turut memunguti kertas-kertas yang mulai meleleh karena air yang menggenang.
────୨ৎ────
Sambil berjalan membuntutnya masuk dalam apartemen, aku meminta maaf atas kejadian seminggu yang lalu. Sebenarnya, kami akan pergi ke restoran setelah tugas kelompok selesai. Namun Julian mendapat telepon–entah apa dan bertanya apakah aku keberatan jika mampir sebentar untuk urusannya. Aku menggeleng dan disinilah kami. Aku duduk di ruang tamu sementara Julian entah, dia di dalam kamarnya, mungkin.
Aku sudah minta maaf tiga kali dan Julian mengatakan tidak apa-apa. Tapi aku tetap merasa bersalah.
Aku menunggunya di ruang tamu hampir 20 menit.
Sambil memperhatikan ruang yang nyaris tak ada apa-apa selain sofa gelap yang kududuki dan satu meja kaca persegi panjang terlihat bersih.
Saat aku menguap ke tiga kali, pria itu baru datang. Aku tidak tahu apa yang dia kerjakan di dalam, saat kembali, dia duduk tepat di sampingku–tidak berjarak dan bahu kami bergesekkan.
“Sorry tunggu lama. Gua tinggal sama mama, dan dia lagi sakit” katanya patetik. Aku mengangguk-angguk mengerti.
Hening beberapa saat. Aku hampir saja berdiri karena ingin segera pergi. Rasanya tidak nyaman berada di rumah laki-laki, pun ini kali pertama bagiku.
“Mau kemana?” Julian mendongak saat aku benar-benar berdiri.
“Ayo pergi, nanti kemaleman” kataku, sambil melirik arloji. Pukul sembilan malam. Dan aku tidak tahu apakah Julian tau posisiku atau dia berhenti sejak aku meneriakinya dalam kamar.
Lenganku di tarik paksa dan aku kembali duduk pada posisi semula. Kurasakan Julian semakin memepet padaku. Desah napasnya menyapu belakang telingaku hangat.
“Sebentar lagi, ya? Dikit lagi” suara itu lagi, begitu lembut mirip permen kapas. Kami diam setelah itu selama hampir setengah menit, sebelum kurasakan bibirnya menyentuh pipiku dalam gerak paling natural dan lambat.
Aku menunduk. Kurasakan degup jantungku berpacu di antara bunyi pendingin ruangan. Pipiku panas dan aku gugup. Aku tidak pernah berkontak seintim ini dengan lelaki.
Saat tangan hangat Julian menyentuh pipi kananku untuk menatap langsung ke matanya, kami nyaris saja berciuman dalam posisi paling ideal. Hanya hampir, sebelum bel pintu berdenting repetitif dan tidak sabaran.
Kami berdehem nyaris berbarengan. Setelah itu, Julian bangkit dengan canggung pergi untuk membuka pintu.
Aku tidak tahu siapa tamunya, tidak mengerti apa yang terjadi, namun suara pukulan terdengar nyaring disusul tubuh Julian limbung nyaris ambruk di depan mataku. Saat ku dongakkan mataku, aku melihat Juan mengenakan pakaian serba hitam, topi dan masker. Dia menatap ke arahku. Sambil membuka masker, dia mengatakan dengan tegas dan tidak terbantahkan.
“Pulang”
────୨ৎ────
Aku menangis sepanjang jalan.
Aku belum mencaci makinya, aku sedang mengumpulkan kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah ada di dunia. Aku juga mengambil napas dalam untuk stok.
“Lu bukan abang gua, bajingan sialan! Lu cuma anak yang nggak di harapkan mami lu sendiri! Lu tau kenapa mami lu milih selingkuh sama laki-laki lain dan menelantarkan lu, huh? Itu karena lu bawa sial. Lu anak nggak berguna dan paling nggak tau diri sedunia. Kalau bukan mami gua yang urus, lu udah mati karena papi lu bahkan sibuk sama kerjaan di banding ngurus anaknya yang useless kek lu”
Aku meneliti tiap garis wajah saat kata-kata menyakitkan itu meluncur lancar tanpa kehabisan napas meski tetap campur tangis. Jangan tanya darimana aku tau kenyataan itu, kenyataan tentang siapa Juan dan alasan aku tidak bisa menghormatinya selayaknya kembaran atau sialan sejenis.
Ya, aku di beri tahu bibi kepala pelayan yang sudah bekerja di rumah sejak aku bayi. Dia menceritakan padaku di tengah malam sebelum kepergiannya kembali ke kampung halaman. Untuk benar-benar berhenti karena anaknya sakit keras.
Itu beberapa tahun silam, tepatnya saat aku baru akan masuk sekolah menengah pertama.
Aku kaget karena kenyataannya, Papi bukanlah ayah kandungku. Dia ayah Juan, tapi bukan ayahku. Sementara Mami adalah ibuku, ayahku meninggal saat aku masih bayi. Bibi kepala pelayan tidak menjelaskan secara detail bagaimana ayah Juan dan ibuku bertemu. Dia melompat pada bagian aku dan Juan yang lahir di tahun dan bulan yang sama. Lantas mereka mendoktrin diri dan semua orang jika aku dan Juan adalah kembar tidak identik. Kami kakak beradik yang harmonis dan saling menyayangi.
Aku tidak berani mengadukan ini pada siapapun apalagi pada Mamiku, tidak pada siapa pun. Kecuali malam ini, dan melihat reaksi Juan yang santai dan terkesan tenang, kupikir dia juga tau kenyataannya, lebih dulu dariku.
Dan hening setelah cacian serta pernyataan dariku. Tangisku tak sebesar tadi.
“Jadi.. please.. Please.. Gua cuma mau hidup senormalnya gadis berusia 22 tahun yang sebentar lagi lulus kuliah. Gua bukan anak kecil yang bisa lu strict secara nggak umum. Gua cuma mau hidup wajar..” aku memohon padanya. Aku benar-benar putus asa.
“Gua bilang, Julian itu bajingan. Dia tidur sama banyak perempuan dan beberapa bahkan hamil dan dia nggak mau bertanggung jawab. Gua akan izinin lu kalau teman lu benar”
Lagi, kata-kata itu lagi. Aku muak.
Juan mengatakan lebih dari 5 kali saat aku berteman dengan Sara. melontarkan omong kosong jika Sara hanya gadis miskin yang pura-pura kaya lalu mendekatiku untuk meminjam uang dan berencana kabur. Aku dengan segenap kewarasan dan kesadaran tentu saja tidak percaya. Kami berteman sangat akrab dan Sara kelewat baik hingga sering membuatkanku makanan dan mengirimkan ke rumah.
Namun tidak lama, ia meminjam uang 800 juta dengan alasan neneknya akan di operasi—mengangkat tumor. Aku dengan lugu mengirimkannya cepat-cepat setengahnya. Kukatakan untuk sabar menunggu karena aku akan meminta pada Papi sisa kurangnya.
Namun dia malah menghilang.
Hilang, pindah. Dia bahkan tidak lagi pergi ke kampus.
Tapi itu Sara.
Sara dan Julian berbeda.
Bukan, bukan itu. Sebenarnya, aku hanya ingin Juan salah. Aku ingin apapun yang keluar dari mulutnya adalah kesalahan, lantas dia di hukum negara atau tuhan. Aku tidak lagi mau melihatnya, astaga. Aku bahkan rela menggadai apapun asal siapapun mau membunuhnya. Aku membencinya sampai ingin mati.
“Kita nggak ada hubungan darah, kita bukan kembar sialan dan lu bukan abang gua” aku menarik ingusku masuk sebelum melanjutkan “jadi please.. Please..”
────୨ৎ────
Kulempar tisu sembarangan. Siapapun yang masuk dalam kamarku, pasti akan tersandung lautan tisu bekas ingus. Satu dua benar-benar beringus, sisanya hanya kuhambur-hamburkan tanpa arti.
Sudah dua hari aku flu. Sejak kejadian malam itu.
Dan pagi ini, Juan masuk dalam kamarku membawakan semangkuk sup dengan aroma paling lezat. Hidungku mampet, namun entah dari mana indra penciumanku menemukan celah hingga kumpulan rempah yang diracik itu menciptakan aroma yang membuat perutku lapar.
Aku tidak bicara pada Juan hingga hari ini. Tidak Juan, juga tidak dengan siapapun karena semua orang di rumah ini adalah pengikut Juan. aku bersumpah, rasanya memang tidak adil ketika semua pelayan, sopir, tukang kebun dan siapapun penghuni rumah ini. Bahkan Mami dan Papi, semua orang begitu patuh dan menyetujui semua hal yang di minta pria itu. Jika pelayan di hadapkan dua perintah antara titahku dan titah Juan, maka, mereka akan patuh pada Juan. Semua, semuanya, aku bersumpah. Atau ini hanya perasaanku karena flu sementara kejengkelanku tak kunjung mereda.
Julian mengirimkan pesan dan mengatakan agar dia dan aku tidak berurusan untuk sementara. Juga menyimpulkan jika Juan tidak suka dengannya. Tidak ada alasan bagi kami bahkan untuk berteman. Namun Julian mengatakan jika nanti ada kesempatana dan Juan membuka hati untuknya di masa depan. Ia akan kembali datang dan ingin bersamaku sebagai sepasang kekasih.
Sialan, aku menjadi lebih jengkel sekali.
“Lu harus makan biar cepet pulih” gumpalan uap dari sup menari-nari di udara. Aku masih bergelung dengan selimut sementara kotak tisu kembali kosong “bentar lagi dokter datang” sambungnya, ini dokter ke tiga. Padahal, aku hanya flu biasa dan akan sembuh saat virus ini hilang.
“Gua harap, lu mati” bisikku lirih. Barangkali Juan mendengarnya hanya seperti gumaman. Maka, ia merangkak naik ke ranjang lalu mendekatkan wajahnya pada wajahku
“Bilang apa? Nggak kedengeran”
Dan aku meludahi wajahnya.
“Bajingan gila, gua aduin Mami, gua benci banget sama lu” aku terisak lagi. Kulihat Juan mengusap wajahnya yang terkena ludah dengan lengan baju. Dia tidak marah atau sejenis–seperti biasa, hanya menghela napas lalu mengambil mangkuk dan mulai menyuapiku telaten.
Aku membencinya.
Membenci sup ini
Membenci flu
Membenci bagaimana Juan tidak marah dengan berbagai aksiku
Membenci ketika pria itu sok dan terus bertingkah dominan
Dan mengapa sup ini begitu enak? Sial.
────୨ৎ────
Dokter ke tiga membuatku benar-benar cepat pulih. Atau katakan obat yang diberikan membunuh seluruh virus keluar bersama ingus pada ribuan lembar tisu. Dan malam ini, aku merasa lebih baik setelah terkapar dua hari tiga malam.
Pukul 01:17.
Aku lapar dan kuyakin semua orang sudah tidur. Kuhidupkan hampir semua lampu–membuat seluruh ruang terang benderang kecuali dapur karena saklar terpisah. Aku mencari apapun yang biasa kumakan. Dan yang pasti, aku tidak bisa masak. Rencanaku hanya mengganjal perut dengan apel atau buah kaya serat lainnya.
Dan saat lampu terakhir hidup, aku kaget setengah mati atas eksistensi orang lain di sana. Hampir terlonjak dan aku tipikal orang yang akan melempar apapun — paling dekat denganku saat kaget.

Tidak, maksudku, ini bukan pemandangan normal yang pernah kulihat seumur hidup. Juan ikut terlonjak saat melihatku. Kami sama-sama kaget namun air mukanya mudah terkontrol, ia sudah terlihat tenang.
“Kok bangun, lapar? Gua lagi buat pasta, mau gak?” katanya ramah. Pipinya naik tinggi. Namun bukan itu, ah sialan. Aku tidak bisa tidak mengedarkan mataku pada otot dada–perut dan paha. Tubuhnya terlihat jauh lebih besar tanpa aling-aling. Dan itu terlalu besar untuk ukuran pria berusia 22 tahun. Aku merasa aku masih kecil. Namun Juan… rasanya seperti dia 5 tahun lebih tua dariku, atau lebih. Tentu saja hanya perasaanku.
Aku menelan ludah untuk aroma pasta. Menciumnya saja perutku semakin lapar. Namun demi harga diriku, aku menggeleng. Kulanjutkan rencanaku mencari buah untuk mengganjal perut yang sama sekali tidak cocok dengan cuaca sedingin ini.
Sial… aku hampir berliur karena lapar dan pasta.
“Jangan makan buah yang banyak air, pilek. Cuaca lagi dingin” pria itu melihatku, aku mengambil apel sebesar dua kepalan tangan dan menggigitnya asal.
Hanya jangan lapar.. Jangan tergoda pasta dan kembali ke kamar.

Berakhir. Disinilah aku duduk, berjarak kurang dari 1 meter dari Juan dan pria itu menyuapiku pasta.
“Makan yang banyak, cepet sembuh” katanya. Satu suapan, satu doa. Dia bahkan tidak tahu jika aku mendoakan kematiannya siang dan malam. Atau tau, namun pura-pura tidak mendengar. Aku juga masih tidak menemukan alasan mengapa dia begitu ngotot ingin berhubungan baik denganku yang sama sekali tidak tertarik—juga tidak ramah. Bahkan setelah caci maki yang kulontarkan mengenai ibunya. Orang waras manapun akan marah. Namun tidak dengan Juan.
“Ada yang lagi di pengen nggak? Abis sakit biasanya nafsu makan ningkat” baiklah, aku mulai menerima saat sendok yang masuk dalam mulutnya, ia gunakan juga untuk menyuapiku. Aku menggeleng lemah, lalu mendongak menatap matanya.
“Gua cuma mau bebas, bebas main, bebas pacaran, bebas menjalin hubungan” lalu menunduk. Aku sedang malas menangis–mengemis hal–hal yang sama berulang-ulang. Dan benar, Juan tidak terlalu menanggapi. Pria itu hanya bengkit mengambil air hangat.
“Mau liburan dulu? Lu stress karena skripsi kan? Ayo ke luar negeri berdua”
Ajakan itu membuat pasta yang baru saja masuk dalam mulutku berhamburan karena batuk. Sebagian masuk dalam hidung. Aku benar-benar tidak mengerti dengan isi kepalanya.
“Lu nggak pernah gagal bikin gua takut” aku menyambung batukku setelah agak reda.
“Kenapa?” tanyanya polos.
“Kenapa? Lu gila ya?”
“Ya, mungkin. Memang kenapa si? Lu kenapa benci banget sama gua coba? Harusnya nggak, lu bukan anak kecil lagi dan bisa liat dan belajar dari yang udah-udah bahwa apa yang gua larang itu jelas nggak baik buat lu” aku melihat jakunnya naik turun saat bicara “sejauh ini, Dena dan Ana adalah yang paling waras. Kalau gua gila dan maunya lu jadi antisosial, gua udah ngurung lu di rumah dan nggak ada satupun orang yang boleh datang untuk bergaul. Kenapa si? Hal-hal sepele aja gak paham. Gua abang lu”
“Lu bukan, berhenti main abang-ade-abang-ade. Kita berdua di rumah ini dan tau siapa kita satu sama lain”
Juan menatapku lama hingga pasta tak segera masuk dalam mulutku. Ia menelisik seakan menusuk bola mataku dengan manik legamnya yang mirip macan.
Lalu bangkit tiba-tiba.
Hanya pergi begitu saja tanpa kata-kata, tanpa sepatah katapun dan meninggalkan sisa pasta yang masih banyak. Tubuh besarnya menghilang saat meniti tangga sampai pangkal.
────୨ৎ────
Kali ini, aku sengaja tidak membawa ponsel ke kampus.
Pun sebenarnya, aku tidak ada kegiatan. Tidak ada kelas, tidak ada tugas. Kedatangaku ke kampus benar-benar ingin pergi bermain dengan Dena dan Ana. pikiranku tentang ponsel yang diretas masih utuh. Aku bersumpah demi nama ibuku, Juan meretasnya meski ini adalah spekulasi liar tanpa bukti. Namun tak perlu bukti saat semua terlalu jelas. Aku hanya berusaha mengakali dengan meninggalkan ponsel—berharap lokasiku tidak terlacak.
Aku pergi ke pantai. Tepatnya kami.
Membawa mobilku, bertiga kami melaju ke pantai yang sedang populer karena baru tiga hari dibuka. Pantai yang menawarkan beberapa fasilitas; ada hotel estetik, ada tempat berjemur yang privat serta pemandangan yang belum tercemar banyak orang. Atau setidaknya, untuk masuk ke dalam sini, aku butuh uang jajanku selama tiga hari.
Tidak, sebetulnya, kami patungan meski aku sudah ngotot akan mentraktir mereka. Tapi tidak di gubris.
Aku menonton bagaimana dua temanku memakai bikini dan menjemur punggung mereka di bawah matahari yang mendung. Aku tidak membuka bajuku, bahkan tidak pernah memperlihatkan bagian atas dadaku pada siapapun. Ana mengatakan bahwa aku akan menjadi pelayan tuhan suatu saat nanti. Pelayan tuhan yang perawan dan suci atau Santa Maria.
Aku duduk di bawah payung besar yang menaungi, menyedot kepala muda yang segar. Angin membawa suraiku meliuk-liuk sementara dress panjang tanpa lengan ikut melambai-lambai. Aku senang hanya karena angin yang membelai tubuhku dengan cara yang tidak bisa di dapatkan dari manapun. Aroma asin yang khas, pantai selalu saja memiliki cara penyembuhan tanpa banyak bicara.
Mudah kaget, aku terlonjak saat seseorang menyentuh bahuku lembut. Yang membuatku nyaris terlonjak adalah dua temanku berada persis di sampingku.
“Hai” katanya.
Lagi, suara itu lagi.
Aku tidak tahu darimana dia mendapat informasi atau Dena memberitahunya. Tapi ada Julian di sini. Dia datang dengan tas yang menepel pada dada, mengenakan setelan yang membuatnya terlihat makin tampan.
“Sorry gua nggak kapok. Sorry untuk bertanya informasi secara paksa dan gua yang merengek ke Dena untuk bisa ketemu lu. Maaf, ya?” alisnya menukik ke bawah. Mungkin saja dia masuk dalam tipe orang yang lebih baik meminta maaf ketimbang meminta izin. Terbukti dengan eksistensinya yang kini duduk di atas pasir–tepat di sampingku.
Tidak kapok akan pukulan Juan. Tidak mundur meski sudah di permalukan. Astaga, aku akan menjadi sangat jahat jika menolaknya. Apa yang sudah di lakukan Juan adalah keterlaluan dan pria ini masih nekat mendatangiku, tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan paling buruk setelah dua kali dikerjai.
Aku tersenyum, menunduk lalu kembali menyedot kelapa muda.
Dia tipe ku.
Pria yang pantang menyerah dan manis.
“Abang lu galak banget buset. Mana badannya kekar, tatoan, tindikan. Tapi gua nggak akan menyerah, gua akan menjilat dia sampe bisa deket sama lu” katanya lagi, ada campur tawa pada kalimatnya.
“Sebenarnya nggak perlu, gua juga benci sama dia, sok ngatur” kataku malas. Dari semua hal, membahas Juan di tempat seindah ini benar-benar merusak suasana. Tawa Julian malah makin kencang.
“Itu tandanya sayang. Keluarga peduli artinya sayang, seorang abang nggak perlu alasan untuk strict ke adenya, gua paham karena gua pernah punya adik, tapi adik gua meninggal karena sakit” terdengar patatik dan aku lagi-lagi menyesal atas pukulan Juan padanya untuk beberapa alasan. Yang pasti, aku tahu bahwa ibunya sakit dan dia kehilangan adiknya karena sakit juga.
Aku mudah mengasihani orang. Kecuali Juan.
Aku mengangguk lagi meski tidak setuju dengan pernyataannya tentang kakak yang menyayangi adik. Juan bukan kakakku, dan kami bukan dalam hubungan seperti kebanyakan orang. Atau hanya aku sendiri yang membencinya? Tidak tahu, aku malas, memikirkannya saja malas.
Kami berbincang lama, kembali membicarakan hal-hal klise, lalu membuat rencana untuk membakar daging nanti malam. Julian akan mengajak beberapa temannya bergabung. Aku setuju saja sementara dua temanku malah makin semangat dan menghubungi pacar mereka masing-masing. Liburan yang tadinya hanya kami bertiga, mendadak ramai dan sialnya, hanya aku sendiri yang tidak memiliki kekasih.
Kami berempat diskusi sebentar. Lalu Julian mulai mengajakku pergi membeli daging dan tetek bengek lain. Rasanya begitu ringkas, tiba-tiba saja jaket Julian menyampir pada punggungku dan tangannya menggenggam milikku lembut. Kami berjalan sebentar hingga pintu keluar pantai — menuju kamar untuk mengambil kunci mobil.
Hanya ke minimarket terdekat.
────୨ৎ────
Aku terbangun dengan rasa berat yang menekan pelipisku, seperti ada tangan tak kasatmata yang terus memutari isi kepalaku. Pandanganku buram. Langit-langit di atasku terlihat berlapis, berbayang, lalu perlahan menyatu. Jelas bukan langit-langit kamarku. Jantungku berdegup lebih cepat begitu kesadaran itu masuk.
Aroma asing menyusup ke hidungku. Bukan kamarku, bukan juga wangi sprei hotel. Ini bau ruangan tertutup—campuran cairan pembersih dan sesuatu yang pahit, menyengat, seperti sisa obat. Tenggorokanku kering. Saat aku menelan, rasa getir masih tertinggal di lidah.
Kepalaku berdenyut hebat ketika aku mencoba menggerakkan tubuh. Rasa sakitnya menjalar dari belakang mata hingga ke tengkuk, membuatku meringis dan kembali memejamkan mata. Dunia terasa miring. Seperti aku baru saja dipaksa keluar dari sesuatu yang terlalu dalam dan gelap.
Aku membuka mata lagi, lebih hati-hati.
Kamar ini… asing.
Dindingnya berwarna pucat, hampir keabu-abuan, dengan satu lampu kecil di sudut yang menyala temaram. Cahaya kuningnya tidak hangat—justru membuat bayangan di ruangan ini terasa lebih panjang dan aneh. Tirai tipis menutup jendela, tapi sinar dari luar nyaris tak menembus. Aku tak tahu jam berapa sekarang, pagi atau malam.
Kasur yang kutempati keras, berlapis seprai polos tanpa motif. Di sampingnya ada meja kecil dari kayu tua, permukaannya penuh goresan halus seperti bekas benda yang sering diletakkan dan diangkat. Di atasnya hanya ada segelas air dan ponsel—bukan ponselku.
Aku menarik napas pendek. Dada terasa sesak.
Ingatanku datang terpotong-potong. Wajah Julian, wajah terakhir yang kulihat dalam mobil. Senyum yang terlalu manis dan mimik patetik yang khas–seperti ketika ia baru menceritakan jika ibunya sakit keras. Suaranya yang terdengar ramah ketika menyodorkan minuman itu. Katanya, aku terlihat dehidrasi meski aku baru saja menelan air kelapa. Namun mustahil kutolak. Lalu rasa hangat dan aneh mengaliri perutku… sesaat dunia perlahan menghilang. Aku tidak ingat apapun, hanya sebatas itu saja.
Aku mencoba duduk, meski kepalaku langsung berdenyut protes. Telapak tanganku dingin, sedikit gemetar. Ini bukan penculikan—aku tidak akan mempercayai isi kepalaku yang berspekulasi. Aku ikut Julian untuk membeli daging. Aku percaya.
Dan sekarang aku terbangun di kamar yang tidak kukenal, dengan tubuh yang masih terasa berat oleh aneh dalam tenggorokan, dan rasa tidak nyaman yang menempel erat di dadaku.
Ada sesuatu yang salah.
Dan entah kenapa, perasaan itu jauh lebih menakutkan daripada jika aku benar-benar diculik.
Di balik pintu, terdengar mekanisme kunci yang bersuara kasar. Seperti besi berkarat yang serat dan dipaksa. Setelah itu, derap berat terdengar mendekat
Aku melihatnya.
Atau tunggu, apa aku terlalu cepat berspekulasi lagi? Tanganku tidak di ikat, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhku kecuali kepala pening bekas pingsan. Barangkali dia akan menjelaskan kesalahpahaman perspektifku.
Julian berdiri di sisi ranjang. Dia tidak lagi menggunakan setelan dengan tas di perut. Melainkan kemeja lengan pendek penuh corak dengan cargo selutut, terlihat santai. Rambutnya tidak klimis oleh pomade–kering dan agak ikal, di sugar ke belakang meski tidak berpengaruh.
Kami berpandangan agak lama sementara aku menunggu penjelasan darinya.
“Hai”
Dan itu bukan kata-kata yang kutunggu. Namun aku berusaha terlihat tenang “hai” jawabku, suaraku seperti tidak keluar semua.
“Sorry kalau kasurnya keras. Disini susah banget, maksudnya, ekspedisi sering gak sampe kalau mesti pesan kasur yang layak. Lu anak orang kaya, pasti terbiasa pakai kasur terbaik, sakit nggak punggungnya?”
Aku masih mencerna perkata. Dan pria itu tidak kunjung menjelaskan situasinya.
“Kita ada dimana?” aku menjawabnya dengan pertanyaan klise–seperti korban penculikan bodoh yang mudah mati. Julian mengeryit, lalu duduk disampingku.
“Di dimana ini ya… di suatu pulau yang harus pakai sampan atau kapal dari hotel yang lu sewa. Perjalanannya butuh 2 jam pakai kapal gede dan 5 jam pakai kapal kecil dan 7 jam pakai sampan. Kita kesini pakai sampan kecil, hanya lu dan gua. Selama 7 jam” ucapannya nyaris membuatku bingung.
Dan ini tidak bagus. Perasaanku makin tidak karu-karuan.
“Kenapa?” aku tidak tahu harus bertanya apa. Aku menunduk, bahkan tidak berani berintonasi tinggi. Siapa yang akan menjamin pria itu tidak memukul atau membunuh? Aku juga memikirkan tentang berita mutilasi yang marak di luar. Tiba-tiba semua hal menjadi menakutkan dan sekarang, aku ingin Juan ada di sini, datang tiba-tiba menggunakan topi dan masker lalu memukuli pria aneh ini. Semuanya menakutkan, aku hampir menangis—masih kutahan.
“Kenapa?” Juan mengulang ucapanku. Ia mendekat–memepet lalu mendoangakkan wajahku. Kulihat gurat-gurat pada tiap inci wajahnya begitu kaku dan geram. Apa dia marah?
“Abang lu mempermalukan gua dua kali. Dia terus mengancam gua dan mengirim pesan aneh hanya karena gua deketin lu. Dia bahkan ngumpulin semua cewek-cewek yang gua hamilin” Julian tertawa “nggak, nggak. Sebenarnya, abang lu udah bagus begitu. Abang yang sayang adik” tertawa lagi, entah apa yang lucu “penciuman dia bagus mirip anjing pelacak. Dia terlalu jeli dan itu bikin gua jengkel. Padahal, kita belum ngapa-ngapain. Dan sial, abang lu malah kirim gua file berisi rekam jejak gua yang nipu ratusan cewek kaya” terbahak-bahak hingga ludahnya muncrat di udara, pria itu seperti orang gila. Dia bukan lagi pria patetik dengan ibu sakit dan adik yang mati karena penyakit.
“Gua di doxing, anjing. Dia ngancam gua bakal sebarin semua info itu kalau gua nggak jauhin lu, sial” lalu Julian berteriak mengagetkan, ia mengumpati Juan dengan seluruh nama binatang.
Ini pertama kali, sumpah. Ini pertama kalinya aku tidak suka Juan di caci maki. Seumur hidupku yang penuh kebencian terhadap kakaku, baru sekali ini saja aku tidak suka umpatan terhadapnya.
Aku kaget dan semakin takut. Ku tatap ubin kusam di bawahku lekat-lekat. Dua tangan terkepal berusaha menguatkan satu sama lain. Aku ketakutan luar biasa.
“T-terus.. Terus lu mau apa, huh? Uang? Gua akan kasih uang asal lepasin gua, biarin gua pulang. Gua akan minta uang ke Papi buat lu, sumpah” itu cara terakhirku, aku tidak tahu harus apa selain menjanjikan uang banyak. Dan sepertinya itulah yang diinginkan Julian.
Pria itu tertawa lagi, seperti stok tawanya begitu banyak dan rahangnya tidak pegal.
Dia menggeleng.
“Nggak-nggak, gua maunya uang dari Juan. Gua yakin uang dia lebih banyak dari lu. Hanya perlu ancam dia dan kirim foto lu, dia akan kasih semuanya.. Mungkin”
Dan itu bukan ide bagus. Setelah itu, Julian memukuliku.
Aku tidak tahu pukulan keberapa. Aku berhenti menghitung ketika rasa sakit tidak lagi berupa. Semuanya berubah jadi denyut di kepala, berdentum seirama dengan jantungku yang panik. Aku merasa hangat—lalu dingin—lalu tidak yakin lagi apa yang kurasakan itu nyata.
Aku memanggil nama Juan di dalam kepala untuk pertama kalinya. Berkali-kali. Seperti mantra. Seperti permohonan terakhir yang mungkin benar-benar akhir.
“Kalau dia sayang,” suara itu mendekat “dia akan bayar mahal.”
Aku ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya napas berat dan penglihatan yang semakin menyempit. Lampu di atas mengecil jadi satu titik terang yang bergetar.
Aku berusaha bertahan.
Satu detik lagi.
Satu napas lagi.
Lalu semuanya jadi terlalu jauh.
Suara menjauh. Rasa sakit menumpul. Tubuhku menyerah lebih dulu daripada pikiranku. Gelap menutup mataku perlahan, seperti aku ditenggelamkan tanpa air.
Pikiran terakhirku sederhana, hampir menyedihkan: aku akan menjadi anak baik dan ramah pada Juan, aku berjanji. Sekali ini saja, aku memohon dia datang… semoga aku masih hidup saat itu. Maka, aku bersumpah akan menjadi adik yang penurut dan ramah meski dia bertingkah menyebalkan.
────୨ৎ────
Aku terbangun begitu saja, tanpa tau bagaimana caranya.
Yang pertama datang bukan penglihatan, tapi bau tajam, Antiseptik. Bau yang terlalu higenis untuk mimpi. Aku menarik napas pelan, dan dadaku terasa berat.
Suara berdengung mengisi kepala. Suaranya mirip pendingin tapi lebih kompleks, mesin yang bekerja terlalu dekat. Aku mencoba membuka mata dan kelopakku terasa lengket dan berat. Meski begitu, aku tetap membuka paksa dua manikku, dan berhasil.
Dunia menyambutku dengan warna pucat; putih, abu-abu, dan cahaya dingin yang memantul dari langit-langit.
Rumah sakit.
Seakan kesadaran datang terlambat, menyusul kebingungan yang lebih dulu menggenang. Aku menatap ke samping—tirai hijau muda setengah tertutup, rel tempat tidur dari besi dingin, selang bening yang menempel di punggung tanganku. Ada plester. Ada jarum. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering dan perih, seperti sudah lama tidak dipakai bicara.
Tubuhku… aneh.
Ini tidak seperti sakit. Tidak, aku tidak pernah merasakan ini. Ini lebih pada lelah sampai ke tulang.
Setiap bagian terasa berbeda. Ada yang berdenyut pelan, ada yang mati rasa, ada yang terasa seperti memar lama yang di senggol. Kepalaku berat, seperti diisi kapas basah. Saat aku sedikit menggerakkan leher, bumi bergoyang, membuatku mual. Aku berhenti, menunggu semuanya diam lagi.
Potongan ingatan menyelip tanpa izin.
Kamar yang asing
Julian
Lantai dingin di pipiku.
Suara tawa dan pukulan Julian yang menakutkan.
Aku mengerjap cepat, napasku tersangkut. Jantungku berdegup lebih kencang, aku ketakutan. Aku merasa aku pernah bangun sebelumnya. Bukan di sini. Bukan dengan bau bersih seperti ini.
Tempat dimana Julian memukuliku.
Dan sekarang, aku di ruangan yang rapi, steril, terlalu tenang. Saking tenangnya, hingga membuatku takut lagi.
Aku mengangkat tangan sedikit. Ototku sakit, seperti tidak terima dan meneriaki bahwa mereka masih harus bekerja. Di pergelangan tanganku ada gelang identitas. Namaku tercetak rapi. Melihatnya membuat dadaku menghangat sekaligus nyeri—aneh, bagaimana satu kata bisa terasa begitu berat.
Aku menoleh lagi. Di sudut ruangan ada kursi kosong. Meja kecil dengan botol air dan tisu. Monitor di samping tempat tidurku berkedip pelan, menunjukkan angka-angka yang sama sekali tak kupahami. Napas terasa dangkal. Setiap tarikan seperti melukai sesuatu di dalam. Ada rasa nyeri tumpul di rahang, di bahu, di sisi tubuh yang sulit kutentukan.
Aku memejamkan mata sebentar.
Bau antiseptik itu konsisten, membawaku sadar akan kenyataan.
Aku selamat.
Oh, betapa ingatan ini membawaku pada peristiwa sebelum kesadaranku direnggut paksa. Aku hidup dan aku berada di tempat aman. Setidaknya, aku tidak perlu ketakutan.
Meski ototku tegang tanpa perintah, cara pikiranku melompat setiap kali ada suara langkah di luar tirai. Aku membuka mata lagi, menatap langit-langit yang terlalu putih.
Sekali lagi, derap langkah mendekat, menyibak pintu hingga derit halus engsel terasa menggaum bagai tongkat malaikat maut yang akan mencabut nyawaku. Aku ketakutan lagi, tubuku bergetar halus dan pacuan jantungku berdetak tidak normal.
Namun saat kulihat pemilik wajah, seluruh ketakutanku luruh menjadi gumpalan debu yang mengambang di antara cahaya yang menyusup dari jendela.
Juan mendekat. Wajahnya panik dan ia segera memanggil dokter saat mata kami terpaut. Dia berteriak dan mengatakan jika aku sadar.
────୨ৎ────
Aku makan dengan lahap.
Hari ke tiga dan hari ini rahangku tidak sakit. Untuk pertama kalinya aku makan dengan normal dan apapun yang masuk dalam mulutku terasa begitu lezat. Atau, sejak kapan menu rumah sakit selezat ini? Apa memang selalu seenak ini?
Juan menyuapiku dengan semangat, aku melihatnya tersenyum berkali-kali. Kami belum bicara sama sekali, kecuali saat dia menawariku untuk ini dan itu—ketika aku bahkan buang air kecil dalam kantong. Selebihnya tidak ada. Tidak ada omelan yang sudah kuprediksi, tidak ada apapun hingga aku sendiri yang menunggu kapan dia akan mengomeliku dan mulai mematihidupkan lampu berulang. Aku sudah bersumpah aku akan bersikap baik padanya.
“Lu bilang ke Mami?” tanyaku untuk pertama kali. Serius, ini percakapan pertama kami diluar keperluan yang krusial. Dia menggeleng. Aku merasa lega.
Bukan lega karena takut Mami atau Papi marah, melainkan lega yang lain. Aku lebih khwatir pada ekspektasiku seandainya Juan mengadukan kondisiku pada kedua orang tua kami dan mereka malah tidak peduli. Itu yang paling aku takutkan. Tidak memberitahu sama sekali malah membuatku lega. Aku tidak harus memikirkan reaksi mereka. Aku hanya takut tidak di pedulikan meski sudah. Hanya Juan yang peduli padaku meski selama ini, aku sangat ngeyel dan kukuh serta terus menganggap jika dia menjijikan.
Tidak, Juan adalah bentuk protesku pada Mami yang benar-benar hilang minat pada anaknya sendiri. Kami benar-benar terasa asing entah sejak kapan. Atau sejak dulu? Aku memiliki sedikit sekali kenang-kenangan serta ingatan tentangnya. Yang paling kuingat adalah ketika aku kelas dua sekolah dasar dan dia memarahiku karena aku memakan jajanan sekolah di luar gerbang. Jenis omelan seperti seorang tetangga yang memarahi anak tetangganya yang lain. Canggung dan hati-hati.
Jika merunut pada sebab aku begitu merindukan atensi dari orang tuaku, semuanya sudah jelas karena mereka disfungsi. Mereka memberi uang dan kehidupan yang sangat layak, namun mereka tidak berperan sebagai ‘orang tua’ selain hanya mesin uang.
Sejak dulu, Juan lah yang paling peduli padaku. Dialah yang selalu sigap dan selalu ada meski beberapa larangannya membuatku benar-benar jengkel. Namun jika di kalkulasi, semua kata-kata hampir 80% adalah prediksi yang tepat. Entah memang bisa membaca orang atau dia serius mencari tahu orang itu, yang pasti, Juan serius saat mengatakan ini baik dan itu buruk.
Aku merenungkan ini sepanjang malam selepas aku siuman pertama kali. Jika tidak ada Juan, mungkin aku sudah mati atau terpuruk atas pergaulanku yang menyedihkan.
Tapi jujur saja, aku tidak memiliki nyali untuk mengatakan maaf atau terima kasih padanya setelah insiden ini. Namun dia jelas membaca perubahanku yang signifikan. Aku tidak lagi bermimik kasar, tidak memberngut dan tidak mendegus jengkel. Aku sering melihatnya dengan wajah menyesal—aku yakin itu ekspresi menyesal. Sumpah.
“Juan”
“Hm?”
“Itu… mmm.. Anu…” aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Makanan sudah habis dan aku sudah minum obat. Dia duduk di sisi ranjang masih menatapku sambil menungguku melanjutkan kalimat.
“Julian gimana?” akhirnya keluar, aku hanya penasaran. Namun Juan justru menatapku aneh, matanya memicing dan sebelah alisnya terangkat tinggi.
“Lu masih berharap gimana? Masih berpikir kalau dia baik kah?” tebaknya lebih terdengar seperti tuduhan, aku juga melihat wajahnya mengeras tidak suka. Padahal bukan seperti itu, aku bertanya karena aku takut jika dia masih berkeliaran di luar dan sewaktu-waktu bisa menculikku lagi.
Aku menggeleng “gua cuma takut.. Takut dia masih ada di sekitar” ucapku pelan, aku menunduk sambil meremas buku jariku kuat-kuat. Lalu aku mendengar Juan menghela napas, ini juga pertama kalinya aku bersuara rendah–mengalah. Biasanya aku selalu merasa paling benar tidak peduli fakta.
Aku sudah janji akan berubah. Aku hanya memiliki Juan.
“Sorry” katanya, suaranya ikut rendah dan lembut. Dia lantas memegang tanganku agar aku berhenti meremasnya kuat-kuat. Membawa jemariku naik ke pipinya. Aku tidak tahu kenapa Juan melakukan itu, tapi aku tidak keberatan. Dia mencium punggung tanganku sambil berlontar maaf.
Pria itu juga merasa aneh saat aku tidak menolak, tidak menepis dan tidak berkata kasar. Tersembuyi, aku tau senyum di balik dehem canggung yang membuatnya tiba-tiba salah tingkah.
“Julian udah di tangkap polisi, dia di penjara” terdengar praktis untuk menenangkan orang panik. Padahal aku tahu jika prosesnya tidak sesepele itu. Namun aku lega, lalu mengangguk mengerti. Mulai hari ini, aku akan mempercayai semua hal yang Juan katakan. Pria itu tidak berdusta, dia jujur dan yang pasti, dia yang akan selalu ada untukku bagaimana pun kondisiku. Satu-satunya manusia yang peduli dan menunaikan tugasnya dengan baik sebagai waliku.
────୨ৎ────
Aku masih mencium bau disinfektan rumah sakit pada ujung gaunku ketika kakiku melangkah masuk ke rumah. Juan memapahku telaten karena setiap gerakan masih terasa nyeri. Memar di tulang rusuk seperti belum berhenti membicarakan apa yang terjadi padaku.
Begitu kaki ku melewati ambang pintu, aroma lembut lilin wangi dan lantai marmer yang baru dipoles menyambutku. Rumah yang selalu rapi, selalu berkilau. Tidak ada satu sudut pun yang terlihat hidup, semuanya teratur dan terlalu hening, kecuali Juan.
Aku menyadarinya saat masuk. Pilar rumah ini adalah Juan. Dia yang menghidupkan suasana, dia adalah tiangnya. Jika dia diam, maka rumah ini hanyalah tembok tinggi dengan udara dingin yang menggantung. Aku hampir mengkategorikannya; benar-benar bukan tempat pulang yang pas.
Sprei rapi di rentangkan tanpa lipatan. Juan menggendongku hingga aku terduduk di posisi paling nyaman sebelum ia berpamitan—ada perkara mendesak sementara air mukanya begitu tegang dan sedikit panik. Geraknya terburu-buru hingga menyenggol ujung pintu. Aku sempat mendengarnya mengaduh sebelum benar–benar menghilang dibalik pintu.
Aku duduk nyaman. Kini, ketimbang rusuk, luka di bahu terasa menarik saat aku menunduk. Meski rasa sakit itu terasa wajar.
Pintu terketuk ketika Juan baru saja pergi.
Aku tidak menjawab karena siapa saja di luar sana jelas akan tetap masuk. Itu pasti pengasuhku atau pelayan. Dan pintu terbuka perlahan.
Ya, pengasuhku. Dia berdiri beberapa langkah dari ambang pintu.
“Jane” suaranya bersih. Terdengar tenang–berbanding dengan ekspresinya. Aku menatap ke jendela, bukan ke arahnya. Dari sana, langit terlihat jingga, sisa matahari yang sebentar lagi tenggelam–masih mampu menembus kaca jendela.
“Pesawat yang di tumpangi Papi dan Mami, jatuh” kalimat tiba-tiba itu menggantung di udara. Mengambang meski tidak hilang arah. Aku baru menatapnya, mencari sesuatu.
Hening setelah itu.
Agak lama.
Ini berita aneh yang tiba-tiba. Aku bersumpah aku baru saja kembali setelah sekarat karena penculikan. Yag kuinginkan—setidaknya Mami menelepon dan menanyakan kabarku meski mustahil.
Bukan kabar sialan ini. Apa katanya? Kenapa tiba-tiba sekali, brengsek.
Sebagian dari diriku menunggu sesuatu. Mungkin gelombang emosi, mungkin kehancuran hati yang umum, atau apapun yang menginterpretasikan kabar duka yang dibawa. Aku malah berharap sesuatu yang lebih menyakitkan dari luka-lukaku sekarang. Aku ingin teralihkan.
Pelan-pelan, telapak tanganku mulai dingin.
“Mereka dinyatakan tewas” katanya presisi. Berita itu lebih terdengar seperti laporan rutin dan entah bagaimana malah terasa paling jujur dibandingkan apapun yang pernah kami miliki sebagai keluarga.
Aku mengangguk, bingung harus apa. Atau kepalaku menolak? Aku kembali menatap jendela. Pikiranku melayang–mengacak-acak ingatan apapun tentang Mami. Katakan ibuku, dia orang tuaku. Tidak masalah jika ayah Juan tidak terlalu perhatian karena memang pada anaknya sendiri pun, dia terlalu dingin. Tapi ibuku, dia yang melahirkan aku, mengapa sikapnya begitu aneh dan dingin? Begitu canggung dan formal. Aku bahkan gagal mengingat kenangan kami karena nyaris tidak ada. Tidak ada, sama sekali. Tidak ada yang istimewa hingga aku bingung harus menangisi apa. Aku bahkan tidak ingin menangis.
Aku bingung.
Ada saat-saat tertentu dalam hidup, dimana dunia terasa tidak bergerak. Semuanya mengambang diam dan hening. Ini bukan jenis tanda kiamat dalam diriku, tapi karena ternyata, tidak ada sesuatu yang perlu bergeser.
Aku menunggu diriku sendiri bereaksi. Menunggu sesuatu pecah, menunggu dadaku terbakar. Tapi sialan yang datang hanya rasa hampa yang kosong.
Akhirnya, aku memikirkan mereka bukan sebagai orang tua. Mereka adalah dua sosok yang selalu bergerak terlalu cepat melewati hidupku. Hotel, bandara, rapat, panggilan telepon yang terlalu singkat serta tatapan sedikit dan terkesan tidak peduli. Dan aku masih mencari sesuatu yang terasa seperti duka. Dan bajingan yang kutemukan adalah kesadaran bahwa hubungan kami tidak serius memiliki bentuk hingga tidak ada yang runtuh sekarang.
Juan masuk buru-buru, geraknya cepat. Dia memelukku.
Ini pertama kalinya. Bukan, ini adalah pelukan pertamaku, aku tidak ingat ada orang yang pernah memelukku selain Juan. Pria itu menangis sedikit. Saat masuk, aku melihat matanya merah meski dia tidak terisak.
Tubuh besarnya hangat mendekapku. Seakan aku mampu masuk ke dalam rengkuhan itu mirip anak kangguru.
Di banding kabar kematian orang tuaku, luka di rusukku lebih menyakitkan. Namun, se-disfungsi apapun mereka, aku harusnya menangis agar terlihat normal.
“Gua ada disini, lu nggak pernah sendirian. Tolong bergantung ke gua mulai hari ini” kata-kata Juan justru yang berhasil membuatku menangis.
Menyadari satu hal jika sejak awal, tempat ku bergantung adalah Juan. Juan adalah rumah ini. Rumahku.
Aku menangis.
Hingga malam.
────୨ৎ────
Juan duduk menyilangkan kaki, tangannya melipat dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya.
Sudah dua minggu sejak kematian dua orang tua kami, dan siang ini, aku dan Juan duduk diruang tamu ketika notaris datang membacakan suarat wasiat—atau entah. Wajah sang notaris terlihat dingin dan aku mengkategorikan jenis ekspresi tidak ramah.
Juan tidak mengatakan apapun. Tapi, bukankah ini tentang warisan? Aku tidak bereaksi signifikan, namun bersaha menyimak apa-apa yang akan di paparkan sang notaris.
Notaris itu akhirnya membuka mapnya. Berdehem sebentar sebelum mulai bicara.
“Sesuai dengan akta perwalian dan dokumen hukum yang tercatat, dua orang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat tersebut tidak memiliki hubungan darah maupun adopsi dengan Saudara Juan.”
Kalimat pembuka, dan aku masih mencerna situasi. Aku celingukan bingung. Lipatan di dahiku pasti mengalahkan tupukan baju dalam lemari. Seperti pembacaan tanggal kematian secara acak–seperti itu kepalaku bereaksi.
“Mereka ditunjuk sebagai wali hukum sementara,” lanjutnya, “atas permintaan dan persetujuan Saudara Juan sendiri, setelah kedua orang tua kandung beliau meninggal dunia, pada saat Saudara Juan masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat hukum untuk mengelola perusahaan serta aset keluarga” Notaris berhenti sejenak, lalu membalik halaman.
“Dengan ini kami nyatakan bahwa seluruh aset—termasuk perusahaan, properti, rekening investasi, dan hak kepemilikan lainnya—secara sah dan penuh kembali kepada pemilik asalnya, yaitu Saudara Juan, usia tiga puluh empat tahun.”
Juan tetap diam. Seolah keputusan ini sudah lama selesai di kepalanya, bahkan sebelum pesawat itu jatuh dari langit. Dan apa katanya? Juan 34 tahun? Apa sih? Aku berharap notaris atau sialan siapapun mau menjelaskan padaku sedikit saja. Ada yang konyol disini.
Aku memalingkan wajah seperti orang dungu, mencoba memahami posisiku sendiri di ruangan itu.
“Adapun Saudari Jane,” aku menunggu saat ini, dan kali ini aku merasa namaku seperti dipanggil dari kejauhan, “berstatus sebagai anak asuh yang diadopsi secara legal oleh Saudara Juan pada usia tiga tahun. Tidak terdapat hak waris atas aset tersebut, kecuali yang secara sukarela diberikan oleh Saudara Juan sebagai wali dan orang tua angkat.”
Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang baru saja meruntuhkan seluruh silsilah hidupku.
Aku bukan adiknya. Kami tidak pernah sedarah. Dan orang tua kami—ternyata bukan orang tua siapa pun.
Sebentar, tolong beri aku napas.
Mami? Mami bagaimana? Aku di adopsi Juan saat berusia 3 tahun? Lalu dimana orang tuaku? Siapa Juan? Kenapa usianya 34 tahun? Dan semua ini milik Juan. Sejak awal. Sejak sebelum aku bisa mengingat apa pun. Sial, aku seperti orang sinting di tempat ini. Aku melihat Juan yang sengaja memalingkan wajah dariku. Pria itu berhutang penjelasan padaku. Padahal, aku sudah bersikap baik sejak sadar bahwa dia adalah kakak terbaik. Namun apa-apaan notaris sialan itu? Apa dia sedang membacakan naskah dongeng?
Notaris menutup mapnya. “Dengan demikian, proses pengalihan aset dinyatakan selesai.”
Hening.
Tidak ada apapun dan sang notaris pergi setelah bersalaman dengan Juan.
Menyisakan hening lagi antara aku dan dia.
Kami bertatapan seperti asing di antara akrab. Seperti malam dan siang. Aku menuntut penjelasan, namun sama sekali tak bernyali. Jantungku berdegup tidak normal dan semua hal terasa bagai omong kosong. Tidak, ini lebih mirip mimpi saat demam.
“Jane” panggilan itu terasa membekukan, aku menatapnya tanpa menjawab “mau dengar cerita sebenarnya?”
Aku mengangguk.
────୨ৎ────
Sejak hari itu, hidupku tak lagi sama.
Aku adalah gadis yatim piatu yang di adopsi oleh Juan saat pria itu berusia 15 tahun lewat wali palsunya. Pertama kali dia melihatku, saat dia sedang mengunjungi panti untuk beramal. Saat itu orang tuanya baru saja meninggal akibat kecelakaan tunggal menuju pulang dari luar kota.
Dia bilang, dia hanya menyukaiku karen aku imut. Lalu ingin agar aku ikut ke rumah.
Dia juga bertanya pada bibi panti tentang orang tuaku. Dan tidak satupun yang tau, aku hanya di tinggalkan di depan pintu panti asuhan tanpa sehelai benang pun, tanpa surat, tanpa nama.
Belum cukup legal untuk menerima semua aset, Juan menunjuk dua orang kepercayaan ayahnya dulu untuk menjadi wali. Menjadi orang tuanya di rumah dengan tugas segunung.
Orang tua palsu; Mami dan Papi.
Mami yang kuanggap adalah ibuku, ibu kandungku sejak kecil. Aku sempat mempertanyakan ocehan kepala pelayan yang mengatakan jika aku dan Juan bukan saudara kandung lantas menggiring narasi lain. Lalu Juan mengatakan jika bibi kepala pelayan mengidap demensia. Itu alasannya di pulangkan, pun anaknya tidak pernah sakit. Melainkan, dia yang terus berdelusi aneh hingga tidak bisa bekerja normal. Maka, sang bibi di pulangkan.
Ini juga membuat hal yang kupercaya sejak aku masuk SMP sia-sia begitu saja. Juan bukan anak Papi palsu, bukan kembaranku, bukan juga kakakku, tapi waliku. Aku adalah anak adopsinya. Dia mengadopsiku dan meminta dua wali palsunya untuk berperan sebagai orang tua kami dan mulai meyakinkan semua orang jika kami kembar.
Lihatlah, aku dan Juan kembar. Itu sudah tidak masuk akal sejak awal. Usia kami terpaut 12 tahun. Dia sudah menyelesaikan semua pendidikannya bahkan saat aku baru kelas 5 sekolah dasar. Pantas mana lagi yang akan ku lamuni? Dia tidak pernah terlihat pergi ke sekolah, tidak juga kuliah. Namun hanya berkutat pada komputer dengan trafik rumit yang sama sekali tidak kumengerti.
Dan semuanya terjawab.
Bagian paling menyedihkan adalah; aku bukan siapa-siapa disini.
Aku tidak memiliki hak apapun di rumah ini. Tidak harta, tidak juga wewenang barang secuil. Rasanya begitu memalukan. Aku malu hingga sulit hanya sekedar mengangkat kepala. Malu merajamku tak kasat mata.
Mengingat bagaimana aku membenci Juan sejak dulu, sejak belia. Bagaimana aku membentak dan mencaci maki, meludahi, dan mendoakannya mati siang dan malam.
Aku malu hingga menangis.
Aku tidak tahu bagaimana menebus rasa malu ini. Rasanya ingin mati saja.
Lalu, bagaimana hidupku setelah ini? Aku ingin sekali pergi saking malunya. Uang dalam tabunganku akan cukup untuk biaya kuliah dan hidup sederhana—meski aku tidak tahu cara hidup sederhana seperti apa.
Aku mulai akan gila, dan kabar ini membuatku mengurung diri dalam kamar selama dua hari.
Tentu saja tidak mungkin. Juan terus masuk, mematihidupkan lampu, menyeret kakiku dan terus mengajakku bicara dan bercanda. Dia kembali pada Juan—kakakku yang paling kubenci. Dia membuatkanku kepiting lada hitam dan tidak ada yang berubah darinya kecuali rasa malu ku yang menyedihkan.
Aku si tidak tahu diri.
“Hentikan, gua mau tidur aja, nggak lapar” kataku merengek, tepat saat Juan menyeret kakiku hingga separuhnya jatuh ke lantai.
“Lu belum makan dari pagi, nanti sakit” nada yang sama, intonasi serupa dan hampir tak ada yang berubah kecuali fakta bahwa usia Juan sangat jauh denganku. Aku bahkan mulai canggung berbahasa informal dengannya.
“Hentikan astaga, gua malu” aku kembali naik ke ranjang. Benar-benar tidak sanggup.
“Malu apa? Emang tukang?” ia terkekeh, aku tidak tahu isi kepala pria dewasa itu. Hampir sepanjang hidupku percaya bahwa kami kembar, usiaku 22 tahun, Juan juga.
Aku bukan adiknya, juga terlalu dewasa menjadi anaknya. Aku mulai krisis identitas di rumah ini.
Dan aku duduk, memberanikan diri menatapnya.
“Gua bukan adik lu, dan terlalu gede untuk jadi anak” aku menunduk, rambutku ikut ke depan semuanya. Juan ikut naik—merangkak ke ranjang untuk menyibak suraiku ke samping–di selipkan di antara telinga. Aku mendongak “gua bukan siapa-siapa. Gua akan pergi dari rumah ini. Gua stress memikirkan ini sampe mual. Ini memalukan dan gua—” aku mendongak menatap langit-langit “dan gua berprilaku buruk selama ini ke lu. Maaf untuk hal-hal kemarin, maaf untuk semua kata-kata kasar dan–” aku tidak sempat melanjutkan kata-kataku. Juan memelukku lebih dulu. Pelukan hangat.
“Gua sayang banget. Jane Juan Jane Juan” ia mengucapkan nama kami berulang-ulang yang kini terdengar indah alih-alih seperti mantra pemanggil setan “gua sayang sama Jane.. tolong jangan ngeyel” dia tertawa lagi.
Memelukku erat, namun tidak pengap. Dia juga mencium pucuk kepalaku.
Aku mendongak dan tatapan kami bertemu.
Aku masuk dalam pupilnya yang segelap malam. Dia bukan kakakku, bukan keluargaku dan dia menyayangiku sedalam ini, sejauh ini. Apa keuntungannya?
Aku tidak akan bertanya, aku malu.
────୨ৎ────
Juan menyambutku pulang kuliah.
Lagi, rambutnya berminyak dan tubuhnya penuh keringat. Senyumnya naik tinggi dan dia membawakan tasku — ikut aku naik ke kamar. Aku tidak lagi sinis–tentu saja, kecuali aku gila. Aku menanggapi candaannya, ikut tertawa dan melempar bantal saat dia mulai iseng masuk dalam kamar untuk mematihidupkan lampu.
“Gua masak udang pedas manis hari ini” suaranya menyusul di belakang. Dia duduk di sisi ranjang saat aku melepas jaketku.
“Kenapa masak terus? Nggak capek apa? Biar bibi aja yang masak” suaraku terdengar ramah, aku mulai terbiasa dengan ini semua.
“Gua mau masakin Jane, gua suka banget pas Jane makan banyak dan lahap sama masakan gua” dia berbaring di ranjangku, dua tangannya merentang. Di saat-saat seperti ini, aku tidak percaya usianya 34 tahun. Mustahil.
Dia terlihat sangat muda. Tatonya yang banyak di sepanjang lengan kanan, tindiknya yang setia di sudut bibir dan alis. Semua begitu pas. Usia 22 tahun terasa pas untuknya.
“Juan”
“Ya?”
“Apa rahasia awet muda?” aku ikut merebah di sampingnya, meletakkan kepalaku pada lengan atasnya yang kekar dan besar. Keringatnya pun khas dan aku suka.
Ini juga baru dan aneh.
“Tips awet muda?” pria itu terlihat berpikir.
Tidak lama.
Juan lalu memeluku “tips awet muda adalah, kaya raya” dia tertawa dengan cara paling menyebalkan–yang mungkin saja jika dulu, aku sudah meludahinya. Namun hari ini, aku ikut tertawa.
Kami sepakat untuk turun dan makan sore bersama.
────୨ৎ────
Aku meringis. Jari kelingkingku berdarah ketika tidak sengaja pisau menyayat sedikit saat aku sedang mengupas apel.
Dan itu tengah malam.
Padahal sudah beberapa lama tidak terbangun tengah malam dan lapar. Lalu kini, pada pukul 00:35, aku berada di dapur sendirian dengan tangan berdarah. Aku mencucinya di wastafel, suara keran berisik membuat fokusku penuh pada darah yang menghilang saat tergerus air, namun keluar banyak saat air mati.
Dan saat aku berbalik, aku kaget setengah mati.
Juan berdiri di belakangku.
Tanpa atasan, hanya celana dalam seperti yang sudah-sudah. Tubuhnya menjulang di depanku bagai raksasa. Sementara matanya lurus pada darah di tenganku. Air mukanya berubah panik.
“Kenapa?”
Aku menceritakan apa yang terjadi. Lalu, dia segera mengambil tanganku, memasukkannya dalam mulutnya, mengulum kelingkingku cepat.
Aku tidak tahu.
Apa mulutnya mengandung paracetamol?

Pria itu membawaku ke dalam pangkuan–duduk di pahanya membelakangi. Dengan telaten, Juan memberikan obat merah dan membebat lukaku setelah membersihkannya.
Aku mengucapkan terima kasih saat rasa perih menghilang bersama bebatan nyaman yang membalut jariku.
Saat aku akan bangun, Juan menahanku.
Kami diam seperti itu beberapa saat, hingga kurasakan napasnya berat menyapu tengkukku.
“Lu lapar kah? Mau makan? Gua buatin makanan” tidak, ini hanya perasaanku saja. Juan berbisik sementara bibirnya menyentuh bagian belakang telingaku. Ini tidak normal. Aku ingin bangkit namun lagi-lagi tangan besarnya menahanku “lu nggak jadi makan apel, kan? Nanti susah tidur kalau belum makan”
Aku bergeming. Otot-otot keras—dada bidang yang kekar–kurasakan menggesek punggungku secara natural. Seperti aku tidak diberi pilihan selain mengangguk–mengiyakan tawarannya.
Baru pria itu melepaskanku.

Bukan pasta.
Kali ini Juan membuatkanku nasi goreng. Ini terlalu sempurna dengan cita rasa luar biasa. Aku melihatnya tersenyum saat menungguku makan. Berkali-kali aku memuji masakannya—mungkin saja perubahanku ini terasa tidak natural–lepas notaris membacakan surat. Namun sejatinya, aku mulai bersumpah pada diriku sendiri untuk bersikap lebih manis pada Juan jika aku selamat dari penculikan amatir dan sinting itu.
Juan menerima sikap dingin dan kejamku selama ini. Semudah itu juga dia menerima perubahan kelewat manis. Seakan tidak peduli jika aku tulus atau hanya takut diusir ke jalanan. Pria itu menerimaku.
Dan aku mulai canggung saat dia terus menatapku dengan pakaian–bukan, dia bahkan tak berpakaian–dengan mata dan ekspresi itu. Sebenarnya, itu mimik lumrah dan biasa, entah sejak kapan aku menjadi perhatian dan terus meraba tiap garis wajahnya.
Tiap detail ekspresi. Pelan-pelan aku tau kapan wajahnya berubah senang saat menatapku. Kapan mengernyit, kapan datar dan seluruh perubahan itu tercatat dalam otakku secara sistematis tanpa perencanaan.
“Jangan liatin gua pakai mata itu” lontaranku membuat Juan menaikkan satu alis. Aku tidak mengerti, sudut pandangku berubah drastis pasca kedatangan notaris–saat semua tersingkap. Juan bukan kembaranku, dan yang paling aneh, dia berusia 34 tahun. Dua orang tua kami adalah kebohongan. Aku sudah memikirkan ini sampai sakit kepala dan yang bisa kulakukan adalah mengingat-ingat seluruh hal aneh hingga semua terhubung bagai benang kusut yang terurai, masuk akal.
────୨ৎ────
Entah siapa yang memulai.
Tidak, aku pasti sinting.
Bukan, aku bersumpah ini bukan karena aku takut diusir dan hidup di jalanan karena setidaknya, jika Juan benar-benar mengusirku, aku masih memiliki setidaknya sisa tabungan untuk hidup layak hingga beberapa bulan ke depan. Aku bersumpah ini bukan karena aku takut di telantarkan.
Tapi Juan membuatku nyaman setelah semua hal.
Setelah makan nasi goreng, setelah aku kembali ke kamar dan membersihkan diri, dia datang ke kamarku. Seperti biasa, mematihidupkan lampu, meledek sambil tertawa. Lalu mulai menarikku yang sudah bergelung dalam selimut. Aku diam saja.
Namun kemudian dia menggigit betisku lembut.
Aku tidak merespons dan dia seperti anak kecil yang sibuk mencari perhatian. Jelas, karena semua aksinya benar-benar kuabaikan. Benar, pandanganku terhadapnya benar-benar jauh berubah hingga kupikir tindakannya yang seperti biasa ini malah aneh.
Tapi aku tetap diam saja.
Dia naik menggigit pelan lenganku, aku konsisten tak menggubris hingga dia datang lalu mencium leher dan rahangku.
Aku tidak tahu harus bereaksi apa. Apa harus meneriakinya? Mencaci maki? Marah-marah?
Aku tau ini pelecehan seksual–atau ya, aku… sialan gila yang menyukai sentuhannya.
Kubiarkan dia melakukan apapun yang dia mau.
Dia mencium bibirku. Bukan ciuman sekilas, dia melumatku pelan. Tubuh tanpa atasan itu tenang di atasku sementara bibirnya memagutku begitu terukur.
Ini ciuman pertamaku.
Dan aku langsung menyukainya sambil memikirkan pria berusia 34 tahun—yang selama ini menghidupiku — berada di atas tubuhku—menginvasi rongga mulutku sangat lembut.
Sial.
Sial.
Ini terlalu murahan tapi aku tidak ingin dia berhenti. Aku menyukainya hingga terbawa arus dan terus mengangguk saat dia bertanya tentang kenyamananku. Apakah aku keberatan atas aksinya, apakah aku baik–baik saja, apa aku suka, dan apakah dia boleh begini dan begitu? Aku terus mengangguk malu-malu. Sungguh, aku tidak bisa membayangkan hal lain saat Juan menyentuhku. Rasanya menyenangkan.
Aku tidak ingat bagaimana pria itu melucuti seluruh gaun tidurku, melempar bra sembarangan dan berhasil membuatku benar-benar bertelanjang sempurna.
Ini pertama juga.
Semua hal, rasanya begitu mendebarkan hingga wajahku panas seperti akan meledak.
Seakan, tubuh bugilku berhasil membakar sesuatu dari diri pria itu. Juan mengukungku, matanya seperti berkilat-kilat dengan deru napas berat yang menyapu wajahku.
Dia membuka kakiku, tangannya sudah bergerilya pada bagian bawah tubuhku dengan jari tengahnya yang meraba bagian vaginaku. Setelah memijat klitoris, sekarang jari tengah itu menusuk-nusuk bagian bibir lubangku.
Mataku membulat saat merasakan jari panjangnya mulai masuk ke liang kewanitaanku setelah sebelumnya hanya mengelus dan menggelitik lubang di antara labiaku.
Bibir kami lagi-lagi bertaut dalam ciuman basah. Aku mengerang merasakan perih. Jari panjangnya membuat gerakkan memutar pada bagian dalamku–melonggarkan kemaluanku yang sudah basah namun sempit.
Rasanya, darahku berdesir semakin cepat. Terlebih ketika Juan membenamkan kepalanya pada ceruk leherku—menggelitik bagian kulit yang sudah di hiasi bercak cinta yang sudah dia buat sebelumnya. Membuatku menggeliat geli ketika lagi dan lagi Juan menjilat dan mengecup bagian itu lagi.
“Lu punya gua.. Jane, mine” dia berujar berat–penuh damba. Bibirnya kembali turun mengecupi tulang selangka dan dadaku. Tangan panasnya meremas payudaraku yang sebelumnya memantul-mantul lembut tiap dia menggerakkan jarinya keluar masuk vaginaku.
Aku hanya menggelinjang, mengerang lagi ketika Juan akhirnya menjamah putingku yang menegang.
“J-juan… ngh! J-Juan hmm” aku menggeliat tak nyaman.
“Lu sempit banget.. sialan” Bergumam pelan, tangannya masih menyodok–mengacak dinding kemaluanku dengan jarinya di bawah sana.
Suhu tubuhku semakin panas, begitu pula Juan.
Kulitku sudah memerah sampai telinga, keringat merembes dari pori-pori karena suhu tubuh yang terus meningkat seiring rangsangan pada vaginaku. Juan masih melakukannya dan aku semakin becek tiap kali dia menekan titik-titik tertentu yang tidak kumengerti dengan jari tengahnya. Menarik, dan menghentakkan jarinya hingga tandas, lututku lemas.
“J-Juan.. Ahh!! – mmhh!!” napasku tak beraturan. Mataku menjuling ke atas kerena rasanya sesuatu mengalir kelewat cepat hingga berkumpul pada vagina — bagai jutaan bintang yang di ledakkan secara bersamaan, aku kejang berulang-ulang. Sesuatu yang hangat keluar dari vaginaku seiring jari panjangnya yang juga keluar.
Pria itu tersenyum, menjilat ujung jarinya dan menaikkan satu alis–mirip orang menganilisa rasa.
Aku tidak tahu—maksudnya, aku benar-benar lemas setelah rasa–ledakkan jutaan bintang di kepalaku dan keluar berbentuk cairan dari vagina. Oke, katakan itu adalah orgasme, aku tau.
Dan kini, Juan bangkit membuka seluruh pakaiannya. Dia membelakangiku–sibuk menunduk entah melakukan apa.
Apalagi?
Dia mamakai lateks.
Benar, aku tidak salah.
Saat berbalik, mataku di suguhkan pemandangan epik. Penis besar itu sudah terbungkus, begitu besar hingga pengaman tak sepenuhnya menyelubungi. Aku menelan ludahku susah payah–setengah skeptis. Aku tau Juan membaca kekhawatiranku, lantas tersenyum padaku. Jenis senyuman yang menginterpretasikan jika semua hal akan baik-baik saja. Meski aku tidak percaya.
Dia kembali menindih tubuhku, memagut lagi bibirku dengan lembut–meremas dada pelan, agak lama.
“Gua suka banget sama lu, dari dulu, dari dulu banget” bisiknya kelewat pelan.
“Sejak kapan?” tanyaku tak kalah pelan.
“Sejak usia lu 3 tahun, awalnya cuma gemes dan kasihan. Tapi makin dewasa–” Juan berhenti. Lalu ia menatap tepat ke dalam mataku “gua suka lu sejak lu SMA. Lu bukan lagi gadis gemes yang menyedihkan, tapi si galak yang lucu. Tiap lu ngomel, tiap lu marah, saat lu mencaci maki. Itu lucu, rasanya pengen gua masukin ke kantong” Juan tertawa. Meski aku bersumpah tidak ada bagian yang lucu. Hampir seumur hidupku kuhabiskan untuk membencinya.
Aku sempat berpikir sekilas, aku takut jika dia adalah pedofil gila yang ternyata menyukaiku sebagai lawan jenis sejak aku bayi. Namun tidak, sepertinya. Mungkin saja dia akan mencabuliku sejak dulu, tapi Juan tidak. Dan malam ini adalah untuk pertama kalinya, pun secara totalitas. Kami bukan hanya berciuman, tapi akan berhubungan seksual. Atau mungkin saja besok pagi aku akan terbangun dan sadar jika semua ini hanya mimpi. Katakan Juan mencampurkan racun ke dalam nasi goreng hingga aku berhalusinasi sehebat ini.
Dan lupakan tentang besok.
“Cuma suka ngomelnya aja? Mulut gua jahat banget padahal” aku mencicit, hanya saja tak akan kubagi tahu jika aku mendoakan kematiannya siang dan malam. Itu terlalu ekstrem.
Juan menggeleng “gua suka semuanya”
Lantas ia memberi jarak di bawahku.
Aku tidak yakin, namun saat kepala batang itu menggesek liangku, aku menggigit bibir bawah. Dia memperhatikan ekspresiku.
“Lu perawan?”
Aku tidak menjawab, namun mengalihkan pandangan. Bagaimana caranya tidak perawan jika dekat lelaki saja Juan selalu ikut campur dan cenderung melarang? Aku pasti akan menjadi suster pelayan tuhan jika bukan pria ini yang melubangiku.
Aku tidak memikirkannya serius. Apalagi ketika Juan mendorong masuk sesuatu yang asing–merangsek ke dalamku. Mataku terbelalak lantas meringis.
Apa ini? Kenapa sakit sekali?
Wajahku panas, lebih panas dari sebelumnya karena ini menyakitkan.
Dalam hentakkan kuat, batang Juan masuk setengahnya. Aku menggelengkan kepala, air mata terjun dari sudut saking perihnya. Dia masih memperhatikan ekspresiku—meski tidak ada yang berubah–maksudnya, pria itu malah menghentak sekuat tenaga–sekali lagi. Lalu amblas sepenuhnya.
“AKKHH!!!! HNNG–UHH” Jeritanku menggema keras ketika daging tebal berwarna coklat kemerahan miliknya akhirnya memenuhiku seutuhnya.
Juan belum bergerak tapi aku lunglai, ku pererat genggaman tanganku pada dua ujung bantal–mencari apapun demi mengurai perih ini barang sedikit.
“Sakit banget ya?” pertanyaan itu.. Kenapa menyebalkan? Air mataku terjun dari sudut kelopak. Vaginaku menegang hingga jepitan itu terasa sesak dan tidak nyaman. Aku melihat Juan sibuk dibawah–entah. Aku bahkan tidak sanggup membayangkan bagaimana dia melihat kemaluanku. Benar, itu memalukan.
Lalu dia memelukku.
“Tarik napas, sayang” katanya lembut. Dia menciumi telingaku hingga geli “jangan tegang, jangan takut, rileks, kendorin dikit, urat lu mau petil ini… santai..” aku tidak tahu apa dia sedang mengajariku meditasi atau terapi. Tapi saat aku berhasil menarik napas, mengendurkan urat-urat serta lebih santai, perih dalam liangku berkurang signifikan. Juan mencolek sesuatu dari sana, sebelum ia mengiming-iming jari tengahnya naik.
Itu darah.
“You belong to me, young lady” Juan menciumku kemudian, ciuman pelan dan lambat, jenis ciuman yang begitu lembut hingga bibirnya seperti meleleh dalam mulutku.
Tubuhnya mulai bergerak ritmis, pelan, terukur dan sangat hati-hati.
Aku terguncang di bawahnya. Pelan-pelan, dalam, terukur dan lambat. Semuanya konstan dan berhasil memaksa bagian bawahku beradaptasi meski tidak sempurna.
Nyeri itu datang dan hilang. Saat Juan menghentak terlalu dalam, aku akan menjerit memekakkan telinganya. Namun yang aneh, tiap rintihan yang keluar dari mulutku, akan membuat pria itu menyeringai, lalu mencium bibirku sekilas dan terus mengatakan bahwa aku cantik dan dia sangat menyukaiku.
Dua tangannya menarik tanganku ke atas.
Aku tidak berdaya, sama sekali. Yang kulakukan hanya meminta Juan selembut mungkin. Dan pria itu begitu pengertian.
Otot-ototnya mengeras, keringat membasahi tubuhnya hingga membuat pahatan itu seakan dilumasi minyak sampai mengkilap. Aku masih saja mencari apapun sebagai pengalihan atas rasa yang tidak terlalu nyaman dalam liangku yang terus di invasi.
Sesak dan penuh.
Juan bilang, aku menjepitnya terlalu keras dan rekat. Aku tidak mengerti. Yang kutahu, penisnya ketat di bawah sana, begitu penuh dan sesak.
Dia mengerang lebih keras, lebih dariku.
Hentakkannya makin liar dan menggila. Aku meminta ampun untuk yang ini karena benar-benar menyakitkan hingga batang itu seperti mengoyak bagian dalam sampai tembus dalam perut bagian atas.
Tubuhku memantul-mantul makin tidak karu-karuan.
Beberapa detik kemudian, erangan Juan menggema bagai singa yang mengaum di tengah hutan. Hujamannya lebih dalam, aku merasakan penisnya berkali-kali lipat lebih besar seakan merobek dinding-dindingku di dalam. Aku tidak lagi berteriak. Aku menangis. Dan terakhir kurasakan miliknya berkedut-kedut di dalam.
Berkedut keras.
Juan hampir ambruk.
Ya, dia menindihku setelah kedutan panjang yang aneh. Terasa asing dalam vaginaku.
“I love you”
Itu kata-kata paling asing yang pernah kudengar seumur hidupku dan Juan adalah yang mengucapkan pertama kali.
Karena orang tuaku yang tidak pernah ada dan tidak pula kutahu dimana mereka—yang seharusnya mengucapkan kata-kata sejenis itu. Seumur hidup, aku hanya hidup dalam kebohongan yang di ciptakan Juan. Kendati demikian, aku bersyukur dan berjanji untuk tidak lagi membencinya apalagi membuat drama yang akan membuatku semakin menyedihkan. Ya, aku bersyukur atas hidupku. Aku tidak terlambat menyadarinya bersama rasa tahu diriku yang membumbung tinggi setelah kematian orang tua palsu kami.
Dan mungkin saja aku mulai nyaman dengan semua tingkah menyebalkan dan kekanakannya. Atau bisa saja ada rasa yang lain. Lebih dari itu.

Goresan Pena
Masih penasaran Julian di apain ya sama Juan?