BAB 3. INI ADALAH CURHATAN HATIKU
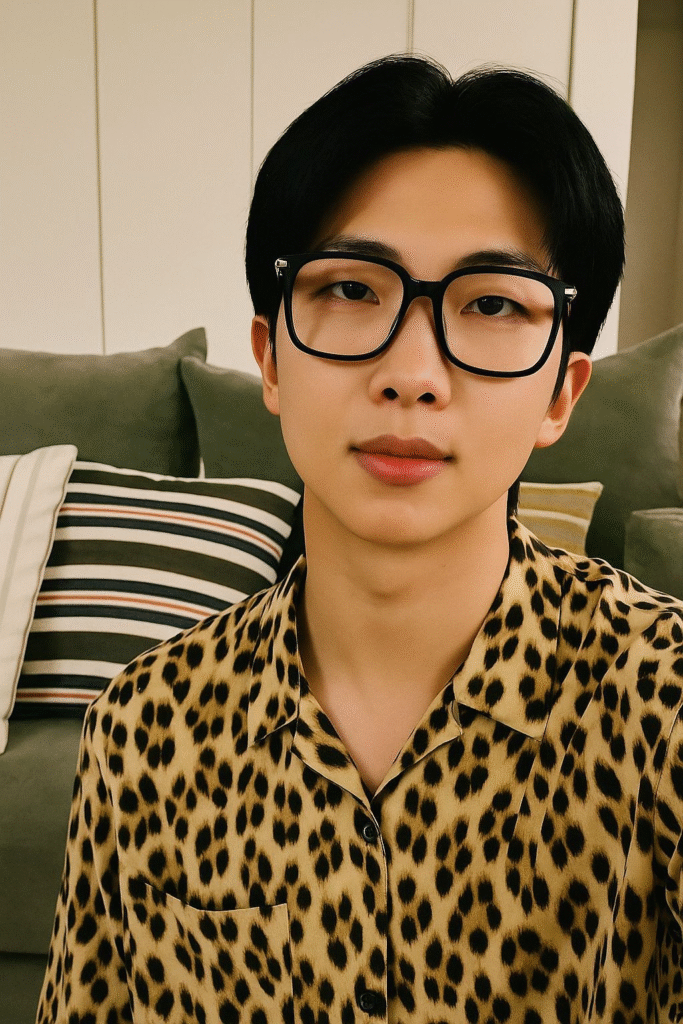
Sebenarnya, aku tidak tahu kenapa aku dilahirkan, kenapa aku berada di keluarga ini dan kenapa aku menjadi anak tengah. Aku paling di dewasa dari 3 adik bungsuku, tapi juga paling bungsu di antara ketiga kakak teratas.
Apakah kekanakan jika aku menganggap bahwa aku adalah orang yang paling tak diperhatikan karena dianggap dewasa dari 3 adikku? Pikiran itu kadang-kadang menyelusup diam-diam saat aku duduk di di kursi belajar sambil mengerjakan tugas sekolah. Duduk berseberangan dengan kembaranku yang selalu pulang dengan wajah lelah.
Kami hanya berjarak 15 menit. Tapi dia seperti 5 tahun lebih tua dariku. Tubuhnya selalu lelah, wajahnya jarang sekali kutemui sumringah, ia selalu memasukkan lembar uang kertas dalam tabungan ayam di lemari selepas pulang kuliah. Aku tidak tahu persis berapa total jumlah uangnya—yang kutahu, aku kalah dari segi finansial dan kecekatan mencari uang. Yang kulakukan adalah belajar, belajar, dan belajar.
Ada malam dimana aku sangat kelaparan. Lalu dua adik bungsuku juga ikut lapar. Aku tak memiliki uang–tak ada pendapatan selain apa yang diberikan kakak tertuaku. Rasanya malu, membangunkan siapapun untuk memberiku makanan. Aku tak ada keterampilan memasak, jangankan memasak, menyalakan kompor saja aku tidak mampu. Lantas, aku hanya memakan nasi dingin dalam mejikom yang sudah berkerak. Dua adikku yang lapar, memakan telur dadar sisa tadi sore dengan nasi yang sudah ku keruk untuk mereka. Jadi, yang bisa kulakukan adalah berterima kasih pada siapa pun yang memasak makanan, aku akan memakannya tanpa mengeluh, meski tempe gosong yang kata orang sudah tak tertolong. Aku berterim kasih.
Aku tidak sedih, aku hanya bertanya, kadang. Kenapa harus aku anak tengah?
Dan pertanyaan itu tidak penting. Hanya sesekali menyelusup.
Mereka, dua kakak tertua, sering berbisik membicarakan masalah perekonomian kami, menggaruk tengkuk dengan desah napas yang menginterpretasikan lelah. Lantas satu sama lain diam, yang satu memegang pundak lalu pergi keluar, juga dilakukan oleh satunya. Mereka akan pergi berjam-jam dan pulang membawakan kami makanan. Aku terkesima, aku selalu berpikir, jika aku dewasa, apa aku bisa sekeren mereka?
Hari-hari berjalan.
Setelah aku menelaah banyak jalan kehidupan dari 3 teratas ku, aku mantap memilih menjadi tidak dewasa. Aku memilih bermain bersama 3 bungsu dan melakukan banyak hal yang jauh dari kata dewasa. Aku belajar, lalu bermain. Aku makan, meski aku tidak akan berebut makanan, aku cenderung menerima, tidak mengeluh, tidak akan.
Dan aku semakin takut saat usiaku bertambah.
Apa aku harus dewasa?
Aku hampir 30 tahun dan aku merasa tidak ada perbedaan antara aku 30 dan aku 19 tahun. Apa ini ironi?
Sebenarnya, kenapa aku menjadi anak tengah? Memahami perasaan kakak tertua, lantas tahu cara bersenang-senang menjadi bungsu. Apa aku aneh? Aku mulai mempertanyakan orientasiku.
Setelah perekonomian keluargaku membaik. Aku mulai berani memantapkan diri; aku ingin menjadi apa yang aku ingin, apakah butuh alasan untuk itu? Aku tidak berencana menikah, aku tidak yakin apa aku bisa menjadi suami atau bahkan ayah. Aku memiliki rumah, rumahku adalah diriku sendiri. Aku baik-baik saja saat sendirian, aku tau bagaimana cara mengatur suasana hati agar tidak kesepian. Tapi, tetap saja tak menampik—ada malam-malam dimana semuanya terasa dingin dan aneh. Seperti king yang berdiri sendirian di atas papan catur setelah berhasil menumbangkan semua lawan—juga pasukanku yang semua tumbang. Sepi, kosong dan dingin.
Aku menampik lagi.
Betapa cinta dan pasangan tidak akan serta merta menghilangkan kekosongan—meski bagi sebagian orang berhasil. Lihat bagaimana hancurnya adikku hanya karena cinta. Lihat bagaimana orang-orang bermulut pedas melabeli para pelajang di usia 30 tahun menjadi begitu menyedihkan. Stigma aneh.
Lalu aku menatap gadis-gadis cantik. Kadang-kadang mengedipkan satu mata berusaha menggoda.
Satu hal yang kupikirkan; apa aku sedang ingin bercinta?
Aku bukan mati rasa, aku hanya tidak butuh. Aku memiliki diriku sendiri.
Aku sedang membayangkan 10 tahun yang akan datang. Rumah kakak tertuaku akan dipenuhi tangis anak kecil yang ramai, tangis keponakanku yang menggemaskan. Bayangkan saja jika satu orang memiliki 2 atau 3 anak. Itu juga menjadi alasan sekaligus pertanyaan, mengapa aku harus menikah? Aku akan memiliki anak secara natural tanpa prosedur semestinya. Rencananya, salah satu dari mereka akan ku doktrin untuk menjadi anakku. Aku pernah memaparkan ini pada si bungsu—tunggu, aku tak mengharap tanggapan yang normal, aku suka celetukannya yang aneh.
Percayalah, hanya Jung yang aneh, aku tidak.
Aku mulai keluar dari pertanyaan tentang ‘mengapa aku anak tengah’ seperti aku sudah berdamai dengan kondisi ini. Lalu, hari-hariku, kuhabiskan dengan melakukan kegiatan yang bagi sebagian orang tak berguna, namun menurutku itu sangat membahagiakan.
Mulai membeli pakaian unik. Pakaian superhero, baju pernikahan adat minang, kostum marching bell, biksu, pastor dan terakhir aku membeli pakaian pria Inggris di abad Renaissance.
Aku memakainya dalam kamar, kadang keluar jika sedang sepi—sekedar meneguk kopi panas menggunakan kain biksu. Sekali, aksiku ini terpergok kakak kedua.
Aku masih ingat kilatan matanya hari itu. Tatapan Yoon seperti—aku sedang mencumbui kekasih sesama jenis, aku pelaku genosida dan aku adalah pencetus perang dunia tiga. Jijik.
Aku mengerti, beberapa orang tersedot dalam garis peraturan yang lurus. Beberapa orang hidup sesuai keinginannya; sepertiku dan beberapa orang diciptakan tuhan untuk menjadi penjahat.
Semua orang dalam perannya masing-masing. Aku merasa, aku adalah NPC. Dan aku senang.
Aku tidak berencana menjadi tokoh utama, jika aku diberi peran, tuhan pasti akan menciptakan masalah untukku, masalah besar. Jadi, aku akan mempersempit keinginan untuk memperkecil masalah. Aku bahagia dengan kehidupanku yang seperti topping ini. Anggap saja aku parutan keju atau matcha bubuk.
Jika aku menginginkan hal besar, maka tuhan akan mengambil hal besar juga.
Aku tidak menginginkannya, karena aku sedih kehilangan apapun. Bahkan sehelai rambutku yang rontok. Aku terlalu nyaman dengan kehidupanku. Jadi, siapapun yang mengatakan ‘keluar dari zona nyaman untuk hidup sukses’ kuharap ia tersedak lada. Hidup nyaman adalah tujuan semua orang. Sementara pengertian sukses sendiri jamak. Aku memilih duduk sambil menyesap kopi dengan tabungan yang cukup sampai aku mati daripada pergi keluar dan menginginkan hal besar yang lantas menukar waktuku yang berharga.
Ini hidupku, jika kamu masih miskin, kamu harus ‘keluar dari zona tidak nyaman untuk masuk ke zona yang lebih tidak nyaman lagi’ hahahaha.
